Teknik Industri
Dasar-dasar Rekayasa Sistem
Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025
Pengetahuan ini dimasukkan ke dalam SEBoK pertama-tama untuk membantu para perekayasa sistem mendapatkan manfaat dari pemahaman dasar-dasar disiplin ilmu mereka, dan untuk memberi mereka akses ke beberapa teori dan praktik ilmu sistem dan bidang-bidang praktik sistem lainnya. Memasukkan konteks ilmu sistem integratif yang lebih luas ini dalam SEBoK juga dapat membantu membuat pengetahuan SE lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas di luar domain tradisionalnya.
Pendahuluan
Sebagian besar insinyur sistem adalah praktisi, yang menerapkan proses dan metode yang telah dikembangkan dan berevolusi selama beberapa dekade. SE adalah pendekatan pragmatis, pada dasarnya bersifat interdisipliner, namun terspesialisasi. Insinyur sistem biasanya bekerja dalam domain tertentu dengan menggunakan proses dan metode yang disesuaikan dengan masalah, kendala, risiko, dan peluang unik domain mereka. Proses dan metode ini telah berevolusi untuk menangkap pengetahuan para ahli domain mengenai pendekatan terbaik untuk menerapkan SE pada domain tertentu.
Domain spesifik di mana pendekatan sistem digunakan dan diadaptasi meliputi:
- Produk teknologi, yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu teknik
- Sistem yang kaya informasi, misalnya komando dan kontrol, manajemen lalu lintas udara, dll.
- Platform, misalnya pesawat terbang, pesawat sipil, mobil, kereta api, dll.
- Sistem organisasi dan perusahaan, yang mungkin difokuskan untuk memberikan layanan atau kemampuan
- Sistem teknik sipil/infrastruktur, misalnya jaringan jalan raya, jembatan, gedung, jaringan komunikasi, dll.
Keahlian khusus untuk setiap domain, serta jenis dan skala sistem yang dipertimbangkan, mungkin sangat berbeda. Namun, ada beberapa prinsip sistem pemersatu yang dapat meningkatkan efektivitas pendekatan sistem dalam domain apa pun. Secara khusus, pengetahuan bersama tentang prinsip dan terminologi sistem akan memungkinkan komunikasi dan meningkatkan kemampuan insinyur sistem untuk mengintegrasikan sistem kompleks yang menjangkau batas-batas domain tradisional (Sillitto 2012). Pendekatan terpadu ini semakin dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan sistem yang kompleks saat ini, tetapi ketika komunitas yang berbeda ini bersatu, mereka mungkin menemukan bahwa asumsi yang mendasari pandangan dunia mereka tidak sama.
Dasar-dasar rekayasa sistem umum
Untuk menjembatani kesenjangan antara domain dan komunitas praktik yang berbeda, penting untuk terlebih dahulu membuat definisi yang beralasan tentang “fondasi intelektual rekayasa sistem,” serta bahasa umum untuk menggambarkan konsep dan paradigma yang relevan. Pendekatan sistem terintegrasi untuk memecahkan masalah yang kompleks perlu menggabungkan elemen-elemen teori sistem dan pendekatan sistem untuk praktik. Hal ini dapat berkisar dari fokus sistem-teknis yang dominan dalam rekayasa sistem hingga fokus sistem-pembelajaran dalam intervensi sistem sosial. Pendekatan sistem terpadu perlu menyediakan kerangka kerja dan bahasa yang memungkinkan berbagai komunitas yang berbeda dengan pandangan dunia dan keahlian yang sangat berbeda untuk bekerja sama demi tujuan bersama.
SEBoK secara keseluruhan bertujuan untuk menyediakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat digunakan untuk mendukung semua aplikasi potensial rekayasa sistem, dan yang dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam aplikasi tertentu oleh pembaca. Seringkali pengetahuan yang dipublikasikan terkait dengan rekayasa sistem telah dikembangkan dari area aplikasi tertentu, biasanya kombinasi dari aplikasi seperti pertahanan, transportasi, atau medis, model bisnis seperti pemerintah, komersial atau sukarela atau domain teknologi seperti mekanik, elektrik, atau cyber. Dalam menerbitkannya, para penulis akan melakukan beberapa upaya untuk mengkhususkannya menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan di berbagai aplikasi terkait.
Dalam SEBoK, kami berusaha untuk menemukan atau membuat deskripsi umum tentang pengetahuan SE. Deskripsi umum harus mencakup semua aplikasi rekayasa sistem dan harus mencakup penjelasan tentang kasus-kasus khusus yang dicakupnya dan bagaimana penerapannya. Generalisasi pengetahuan dapat bersifat informal, memberikan cakupan spesialisasi yang paling umum atau menjadi domain pemahaman terbaik saat ini tentang kasus umum. Deskripsi yang benar-benar umum harus didasarkan pada pertimbangan teoritis yang lebih kuat dan dalam beberapa hal terbukti dapat memprediksi dan mencakup semua kasus khusus. Pengetahuan yang dijelaskan dalam SEBoK biasanya merupakan pengetahuan umum yang digeneralisasi secara informal, dengan pengetahuan khusus yang diidentifikasi seperti itu dan terkait dengan pengetahuan umum sebagaimana mestinya.
Visi INCOSE 2025 mencakup tujuan agar rekayasa sistem menjadi sebuah disiplin ilmu dengan dasar teori yang didefinisikan secara formal. Teori umum SE seperti itu sebagian besar akan dimasukkan dalam SEBoK Bagian 2. SEBoK bagian 2 saat ini tidak menyertakan teori seperti itu. Ini memberikan deskripsi umum tentang pengetahuan dasar yang memiliki nilai pragmatis untuk membantu menggambarkan dan meningkatkan praktik rekayasa sistem saat ini dan di masa depan. Kami mengharapkan teori umum rekayasa sistem yang muncul untuk menarik dan memperluas fondasi ini. Ketika teori tersebut didefinisikan, teori tersebut akan dimasukkan ke dalam Bagian 2 dari SEBoK.
Kerangka kerja praksis sistem
Istilah “praksis sistem” mengacu pada seluruh upaya intelektual dan praktis untuk menciptakan solusi holistik untuk tantangan sistem yang kompleks saat ini. Praksis didefinisikan sebagai “menerjemahkan ide ke dalam tindakan” (Wordnet 2012) dan menunjukkan bahwa pendekatan holistik terbaik untuk tantangan kompleks yang diberikan mungkin memerlukan pengintegrasian teori yang tepat dan praktik yang sesuai dari berbagai sumber. Praksis sistem membutuhkan banyak komunitas untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama, pertama-tama kita harus berkomunikasi; dan untuk berkomunikasi, pertama-tama kita harus terhubung.
Kerangka kerja untuk menyatukan praksis sistem dikembangkan oleh anggota International Council on Systems Engineering (INCOSE) dan International Society for the System Sciences (ISSS) (Federasi Internasional untuk Penelitian Sistem (IFSR) 2012) sebagai langkah pertama menuju “bahasa umum untuk praksis sistem”. Kerangka Kerja Praksis Sistem ini disertakan di sini karena mewakili pemikiran terkini tentang dasar-dasar dan bahasa umum rekayasa sistem, sehingga konsep dan prinsip pemikiran dan praktik sistem dapat diakses oleh siapa pun yang menerapkan pendekatan sistem untuk masalah sistem rekayasa. Kerangka kerja dan pemikiran ini telah digunakan untuk membantu mengorganisir panduan pengetahuan sistem dalam SEBoK.
Diagram di bawah ini menunjukkan aliran dan interkoneksi di antara elemen-elemen “ekosistem pengetahuan” dari teori dan praktik sistem.

Sumber: sebookwiki.org
Gambar 2. Kerangka Kerja Praksis Sistem, Dikembangkan sebagai Proyek Bersama INCOSE dan ISSS. (© 2012 Federasi Internasional untuk Penelitian Sistem) Dirilis di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons 3.0. Sumber tersedia di http://systemspraxis.org/framework.pdf.
Dalam kerangka kerja ini, elemen-elemen berikut ini saling berhubungan:
Pemikiran Sistem adalah elemen integratif inti dari kerangka kerja ini. Kerangka kerja ini mengikat fondasi, teori, dan representasi dari ilmu sistem bersama dengan pendekatan keras, lunak, dan pragmatis dari praktik sistem. Dalam praksis sistem, seperti halnya dalam disiplin ilmu praktis lainnya yang didukung oleh ilmu pengetahuan, terdapat interaksi yang konstan antara teori dan praktik, dengan teori yang menginformasikan praktik dan hasil dari praktik yang menginformasikan teori. Pemikiran sistem adalah kegiatan berkelanjutan dalam menilai dan menghargai konteks sistem, dan memandu adaptasi yang tepat, di seluruh siklus praksis.
Ilmu Sistem Integratif memiliki cakupan yang sangat luas dan dikelompokkan ke dalam tiga bidang:
- Fondasi, yang membantu mengorganisir pengetahuan dan mendorong pembelajaran dan penemuan. Area ini meliputi: meta-teori metodologi, ontologi, epistemologi, aksiologi, praksis (teori tindakan efektif), teleologi, semiotika & semiosis, teori kategori, dan lain-lain.
- Teori-teori yang berkaitan dengan sistem disarikan dari domain dan spesialisasi, sehingga dapat diterapkan secara universal: teori sistem umum, patologi sistem, kompleksitas, sistem antisipatif, sibernetika, autopoiesis, sistem kehidupan, ilmu desain generik, teori organisasi, dll.
- Representasi dan teori yang sesuai menggambarkan, mengeksplorasi, menganalisis, dan membuat prediksi tentang sistem dan konteksnya yang lebih luas, baik dalam hal model, dinamika, jaringan, cellular automata, siklus hidup, antrian, grafik, gambar yang kaya, narasi, permainan dan drama, simulasi berbasis agen, dll.
Pendekatan Sistem untuk Praktik bertujuan untuk bertindak berdasarkan pengalaman dunia nyata untuk menghasilkan hasil yang diinginkan tanpa konsekuensi yang merugikan dan tidak diinginkan; oleh karena itu, praktik perlu memanfaatkan berbagai macam pengetahuan yang sesuai dengan sistem yang diminati dan konteks yang lebih luas. Tidak ada satu cabang ilmu atau praktik sistem yang memberikan penjelasan yang memuaskan untuk semua aspek “problematika” sistem yang khas; oleh karena itu, pendekatan yang lebih pragmatis diperlukan. Pendekatan sistem tradisional sering digambarkan sebagai pendekatan keras atau lunak:
- Pendekatan keras cocok untuk memecahkan masalah yang terdefinisi dengan baik dengan data yang dapat diandalkan dan tujuan yang jelas, menggunakan metode analitis dan teknik kuantitatif. Sangat dipengaruhi oleh metafora “mesin”, pendekatan ini berfokus pada sistem teknis, kompleksitas tujuan, dan optimasi untuk mencapai kombinasi yang diinginkan dari sifat-sifat yang muncul. Pendekatan ini didasarkan pada fondasi dan pandangan dunia “realis” dan “fungsionalis”.
- Pendekatan lunak cocok untuk menyusun masalah yang melibatkan data yang tidak lengkap, tujuan yang tidak jelas, dan pertanyaan terbuka, menggunakan metafora “sistem pembelajaran”, fokus pada komunikasi, kompleksitas intersubjektif, interpretasi dan peran, dan mengacu pada filosofi subjektif dan “humanis” dengan dasar konstruktivis dan interpretivis.
- Pendekatan pragmatis (pluralis atau kritis) secara bijaksana memilih seperangkat alat dan pola yang sesuai yang akan memberikan wawasan yang cukup dan tepat untuk mengelola masalah yang dihadapi dengan menerapkan beberapa metodologi yang diambil dari berbagai dasar yang sesuai dengan situasi. Heuristik, kritik batas, model yang sedang berlangsung, dll, memungkinkan pemahaman tentang asumsi, konteks, dan kendala, termasuk kompleksitas karena nilai dan penilaian pemangku kepentingan yang berbeda. Perpaduan yang tepat antara metode “keras”, “lunak”, dan metode khusus yang mengacu pada sistem dan tradisi spesifik domain. Sistem dapat dipandang sebagai jaringan, masyarakat agen, organisme, ekosistem, rimpang, wacana, mesin, dll.
Kumpulan “awan” yang secara kolektif mewakili praksis sistem adalah bagian dari ekosistem pengetahuan, pembelajaran, dan tindakan yang lebih luas. Integrasi yang berhasil dengan ekosistem yang lebih luas ini adalah kunci keberhasilan dengan sistem dunia nyata. Ilmu sistem dilengkapi dengan disiplin ilmu “keras”, seperti fisika dan ilmu saraf, dan dengan disiplin ilmu formal, seperti matematika, logika, dan komputasi. Ilmu ini juga diperkuat oleh, dan digunakan dalam, disiplin ilmu humanistik, seperti psikologi, budaya, dan retorika, serta disiplin ilmu pragmatis, seperti akuntansi, desain, dan hukum. Praktik sistem bergantung pada data yang terukur dan metrik tertentu yang relevan dengan situasi dan domain masalah, permintaan nilai-nilai dan pengetahuan lokal, dan integrasi pragmatis dari pengalaman, praktik-praktik terdahulu, dan pengetahuan disiplin ilmu.
Singkatnya, Ilmu Sistem Integratif memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memahami pola kompleksitas melalui kontribusi dari fondasi, teori, dan representasi ilmu sistem dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan “masalah”. Pendekatan Sistem untuk Praktik menangani masalah dan peluang yang kompleks dengan menggunakan metode, alat, kerangka kerja, pola, dll., yang diambil dari pengetahuan ilmu sistem integratif, sementara pengamatan terhadap hasil praktik sistem meningkatkan tubuh teori. Berpikir Sistem mengikat keduanya melalui praktik yang apresiatif dan reflektif dengan menggunakan konsep, prinsip, pola, dll.
Cakupan bagian 2
Bagian 2 dari SEBoK berisi panduan pengetahuan tentang sistem, yang relevan dengan pemahaman yang lebih baik tentang SE. Bagian ini tidak mencoba untuk menangkap semua pengetahuan sistem di sini; melainkan memberikan gambaran umum tentang sejumlah aspek kunci dari teori dan praktik sistem yang sangat relevan dengan SE.
Organisasi pengetahuan di Bagian 2 didasarkan pada Kerangka Kerja Praksis yang telah dibahas di atas (IFSR 2012). Kebutuhan untuk mengembangkan panduan yang jelas tentang pengetahuan yang mendasari SE merupakan salah satu motivasi di balik kerangka kerja praksis. Diharapkan cakupan pengetahuan sistem akan meningkat secara signifikan dalam versi SEBoK yang akan datang seiring dengan berjalannya pekerjaan ini.
Diagram berikut ini merangkum cara bagaimana pengetahuan dalam SEBoK Bagian 2 disusun.

Sumber: sebookwiki.org
Gambar 3. Hubungan antara Ide-ide Sistem Utama dan SE. (Sumber: SEBoK Asli)
Diagram ini dibagi menjadi lima bagian, masing-masing menggambarkan bagaimana pengetahuan sistem diperlakukan dalam SEBoK.
- Area Pengetahuan Dasar Sistem mempertimbangkan pertanyaan “Apa itu Sistem?” dari sudut pandang Insinyur Sistem. Bagian ini mengeksplorasi Konsep, Prinsip, dan Heuristik Rekayasa Sistem dan bagaimana hal ini berhubungan dengan proses pengembangan ilmiah. Berbagai macam definisi sistem diperkenalkan, termasuk perbedaan antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan jenis-jenis sistem yang direkayasa. Semua ide ini sangat relevan dengan sistem rekayasa dan pengelompokan sistem tersebut yang terkait dengan pendekatan sistem yang diterapkan pada sistem rekayasa (yaitu sistem produk, sistem layanan, sistem perusahaan, dan sistem sistem).
- Area Pengetahuan Sifat Sistem menyediakan titik masuk ke dalam lanskap yang kaya akan sistem (alami dan rekayasa) di alam semesta. Di tengah keragaman ini, kami menyuarakan dan membuat pola-pola yang teramati secara eksplisit yang bersifat universal untuk semua sistem. Studi tentang pola-pola inilah yang membentuk premis untuk ilmu sistem dan fondasi di mana pemikiran sistem dan rekayasa sistem suatu hari nanti akan sepenuhnya didasarkan.
- Area Pengetahuan Ilmu Sistem menyajikan beberapa pergerakan yang berpengaruh dalam ilmu sistem, termasuk perkembangan kronologis ilmu sistem dan teori-teori yang mendasari di balik beberapa pendekatan yang diambil dalam menerapkan ilmu sistem pada masalah-masalah nyata.
- Area Pengetahuan Pemikiran Sistem menjelaskan konsep, prinsip, dan pola utama yang digunakan dalam penelitian dan praktik sistem. Pemikiran sistem adalah paradigma mendasar yang menggambarkan cara memandang dunia. Orang-orang yang berpikir dan bertindak dengan cara sistem sangat penting untuk keberhasilan penelitian dan praktik disiplin sistem. Secara khusus, individu yang memiliki kesadaran dan/atau keterlibatan aktif dalam penelitian dan praktik disiplin ilmu sistem diperlukan untuk membantu mengintegrasikan kegiatan yang terkait erat ini.
- Area Pengetahuan Representasi Sistem dengan Model mempertimbangkan peran kunci yang dimainkan oleh model abstrak dalam pengembangan teori sistem dan penerapan pendekatan sistem.
- Pendekatan Sistem yang Diterapkan pada Area Pengetahuan Sistem Rekayasa mendefinisikan pendekatan terstruktur untuk penemuan, eksplorasi, dan resolusi masalah/peluang, yang dapat diterapkan pada semua sistem rekayasa. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran sistem dan menggunakan elemen-elemen yang sesuai dari pendekatan dan representasi sistem. KA ini memberikan prinsip-prinsip yang memetakan secara langsung ke praktik SE.
Pengetahuan yang disajikan dalam bagian SEBoK ini telah diorganisasikan ke dalam area-area tersebut untuk memudahkan pemahaman; tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang penelitian dan praktik berdasarkan pengetahuan sistem. Bidang-bidang pengetahuan ini harus dilihat bersama-sama sebagai “sistem gagasan” untuk menghubungkan penelitian, pemahaman, dan praktik, berdasarkan pengetahuan sistem yang mendasari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, manajemen, dan teknik dan berlaku untuk semua jenis domain.
Disadur dari: sebookwiki.or
Elektronika
Profil Perusahaan Foxconn
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 28 Februari 2025
Hon Hai Precision Industry Co, Ltd, yang diperdagangkan sebagai Hon Hai Technology Group di Tiongkok dan Taiwan serta Foxconn secara internasional, adalah produsen kontrak elektronik multinasional Taiwan yang didirikan pada tahun 1974 dengan kantor pusat di Tucheng, New Taipei City, Taiwan. Pada tahun 2021, pendapatan tahunan perusahaan mencapai 6,83 triliun dolar Taiwan (US$214 miliar) dan menduduki peringkat ke-20 dalam Fortune Global 500 tahun 2023. Perusahaan ini merupakan produsen kontrak elektronik terbesar di dunia. Meskipun berkantor pusat di Taiwan, perusahaan ini memperoleh sebagian besar pendapatannya dari aset di Tiongkok dan merupakan salah satu pemberi kerja terbesar di seluruh dunia. Terry Gou adalah pendiri dan mantan ketua perusahaan.
Foxconn memproduksi produk elektronik untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika, Kanada, Cina, Finlandia, dan Jepang. Produk terkenal yang diproduksi oleh Foxconn termasuk BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Kindle, semua sistem game Nintendo sejak GameCube, model Nintendo DS, model Sega, perangkat Nokia, produk Cisco, perangkat Sony (termasuk sebagian besar konsol game PlayStation), perangkat Google Pixel, perangkat Xiaomi, semua penerus konsol Xbox Microsoft, dan beberapa soket CPU, termasuk soket CPU TR4 pada beberapa motherboard. Pada tahun 2012, pabrik Foxconn memproduksi sekitar 40% dari semua barang elektronik konsumen yang dijual di seluruh dunia.
Foxconn menunjuk Young Liu sebagai ketua barunya setelah pengunduran diri sang pendiri, Terry Gou, yang berlaku efektif pada 1 Juli 2019. Young Liu adalah asisten khusus untuk mantan ketua Terry Gou dan kepala grup bisnis S (semikonduktor). Para analis mengatakan bahwa serah terima jabatan ini menandakan arah masa depan perusahaan, menggarisbawahi pentingnya semikonduktor, bersama dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan mengemudi otonom, setelah bisnis utama tradisional Foxconn, yaitu perakitan ponsel pintar, semakin matang.
Sejarah
Terry Gou mendirikan Hon Hai Precision Industry Co, Ltd sebagai produsen komponen listrik pada tahun 1974 di Taipei, Taiwan. Pabrik manufaktur pertama Foxconn di Tiongkok Daratan dibuka di Kota Longhua, Shenzhen, pada tahun 1988.
Salah satu tonggak penting bagi Foxconn terjadi pada tahun 2001 ketika Intel memilih perusahaan ini untuk memproduksi motherboard bermerek Intel, bukan Asus. Pada bulan November 2007, Foxconn semakin berkembang dengan mengumumkan rencana untuk membangun pabrik baru senilai US$500 juta di Huizhou, Cina Selatan.
Pada bulan Januari 2012, Foxconn menunjuk Tien Chong (Terry) Cheng sebagai kepala eksekutif anak perusahaannya, FIH Mobile Limited. Pada saat itu, Foxconn memproduksi sekitar 40% dari produksi elektronik konsumen di seluruh dunia.
Ekspansi lebih lanjut diupayakan setelah pada bulan Maret 2012, Foxconn mengakuisisi 10% saham perusahaan elektronik Jepang, Sharp Corporation, dengan nilai US$806 juta dan membeli hingga 50% LCD yang diproduksi di pabrik Sharp di Sakai, Jepang. Namun, kesepakatan yang telah disepakati tersebut batal karena saham Sharp terus merosot di bulan-bulan berikutnya. Pada bulan September 2012, Foxconn mengumumkan rencana untuk menginvestasikan US$494 juta untuk pembangunan lima pabrik baru di Itu, Brasil, yang akan menciptakan 10.000 lapangan kerja.
Pada tahun 2014, perusahaan ini membeli Asia Pacific Telecom dan memenangkan beberapa lisensi spektrum dalam sebuah lelang, yang memungkinkannya untuk mengoperasikan peralatan telekomunikasi 4G di Taiwan.
Pada tanggal 25 Februari 2016, Sharp menerima tawaran pengambilalihan senilai ¥700 miliar (US$6,24 miliar) dari Foxconn untuk mengakuisisi lebih dari 66 persen saham Sharp. Namun, karena Sharp memiliki kewajiban yang tidak diungkapkan yang kemudian diinformasikan oleh perwakilan hukum Sharp kepada Foxconn, kesepakatan tersebut dihentikan oleh dewan direksi Foxconn. Foxconn meminta untuk membatalkan kesepakatan tersebut, namun tetap dilanjutkan oleh mantan presiden Sharp. Terry Gou, dalam pertemuan tersebut, kemudian menulis kata "義", yang berarti "kebenaran", di papan tulis, mengatakan bahwa Foxconn harus menghormati kesepakatan tersebut. Sebulan kemudian, pada tanggal 30 Maret 2016, kesepakatan tersebut diumumkan telah selesai dalam sebuah pernyataan pers bersama, namun dengan harga yang lebih rendah.
Pada tahun 2016, Foxconn, bersama dengan Tencent dan dealer mobil mewah Harmony New Energy Auto, mendirikan Future Mobility, sebuah perusahaan rintisan mobil yang bertujuan untuk menjual mobil premium yang sepenuhnya otonom dan bertenaga listrik pada tahun 2020. Unit Foxconn, Foxconn Interconnect Technology, mengakuisisi Belkin International senilai $866 juta pada 26 Maret 2018.
Pada bulan Juli 2019, Foxconn menunjuk Liu, Young-Way sebagai ketua baru Grup, yang saat itu menduduki peringkat ke-25 di antara 100 Perusahaan Digital Teratas Forbes. Segera setelah itu, Foxconn, yang dipimpin oleh Young Liu, memperkenalkan Model Transformasi "3+3", yang memprioritaskan tiga industri utama: kendaraan listrik, kesehatan digital, dan industri robotika. Grup ini juga berkomitmen untuk mengembangkan kecerdasan buatan, semikonduktor, dan teknologi komunikasi generasi mendatang, yang merupakan blok bangunan dalam strategi teknologi Grup.
Pada tahun 2020, Foxconn mendirikan "Hon Hai Research Institute", dengan lima pusat penelitian, yang masing-masing memiliki rata-rata 40 profesional R&D teknologi tinggi, yang semuanya difokuskan pada penelitian dan pengembangan teknologi baru, penguatan teknologi Foxconn, dan jalur inovasi produk, upaya untuk mendukung transformasi Grup dari "otot" menjadi "otak", dan peningkatan daya saing strategi "3+3" Foxconn.
Pendapatan Foxconn pada tahun 2020 adalah NT$5,36 triliun (US$193 miliar). Majalah Circuits Assembly menobatkan Foxconn sebagai perusahaan jasa manufaktur elektronik terbesar di dunia selama 14 tahun berturut-turut.
Pada tanggal 5 Februari 2020, Foxconn mulai memproduksi masker medis dan pakaian di pabriknya di Shenzhen, Tiongkok, selama Tahun Baru Imlek dan puncak pandemi COVID-19. Perusahaan awalnya mengatakan bahwa masker yang dibuatnya akan digunakan untuk karyawan internal. Merebaknya penyakit virus corona 2019 menyebabkan lonjakan permintaan masker di seluruh dunia, yang mengakibatkan kelangkaan global. Dalam sebuah surat kepada karyawan, Chairman Young Liu berkata, "Saya ingat dengan jelas betapa menyentuhnya saat Longhua Park memproduksi masker pertama kami pada pukul 4:41 pagi tanggal 5 Februari. Itu adalah produk paling sederhana namun paling penting yang pernah dibuat Foxconn. Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kelompok untuk pencegahan epidemi, tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat umum dan meningkatkan moral kelompok. Semua itu merupakan hasil dari kerja keras rekan-rekan kami."
Setelah hampir satu tahun kontroversi publik terkait kekurangan vaksin COVID-19; pada Juni 2021, Taiwan setuju untuk mengizinkan pendiri Terry Gou, melalui badan amal Yongling Foundation, untuk bergabung dengan pembuat chip kontrak TSMC, dan menegosiasikan pembelian vaksin COVID-19 atas namanya. Pada Juli 2021, agen penjualan BioNTech di Tiongkok, Fosun Pharma, mengumumkan bahwa Foxconn dan TSMC telah mencapai kesepakatan untuk membeli 10 juta vaksin COVID-19 BioNTech dari Jerman untuk Taiwan. Kedua produsen teknologi tersebut berjanji untuk masing-masing membeli lima juta dosis dengan nilai hingga $175 juta, untuk disumbangkan ke program vaksinasi Taiwan.
Pada tahun 2020, Foxconn memprakarsai MIH Alliance untuk menciptakan ekosistem EV terbuka yang mendorong kolaborasi dalam industri mobilitas, dengan lebih dari 2.200 perusahaan telah bergabung dengan standar terbuka tersebut sejak diluncurkan. Perusahaan ini mengumumkan rencana untuk lebih terlibat sebagai perakit kontrak mobil listrik. Pada tahun yang sama, Foxconn bermitra dengan Fiat Chrysler Automobiles N.V. dan Yulon Group untuk masuk ke mobil listrik. Foxconn telah menyelenggarakan acara Hon Hai Tech Day (HHTD) sejak tahun 2020 untuk memamerkan pencapaian terbarunya. Pada HHTD21, Foxconn memperkenalkan untuk pertama kalinya tiga model mobil listrik yang dikembangkan sendiri: kendaraan rekreasi Model C, sedan Model E, dan bus listrik Model T.
Pada Januari 2021, Foxconn dan Geely Holding Group menandatangani perjanjian kerja sama strategis dan akan mendirikan perusahaan patungan untuk menyediakan OEM dan layanan konsultasi khusus yang berkaitan dengan seluruh kendaraan, suku cadang, sistem penggerak cerdas, dan platform ekosistem otomotif untuk perusahaan otomotif global dan perusahaan berbagi tumpangan. Pada bulan Februari 2021, Foxtron mengumumkan perjanjian dengan perusahaan rintisan kendaraan listrik Fisker Inc. untuk bersama-sama memproduksi lebih dari 250.000 kendaraan per tahun. Pada bulan Maret 2021, Foxtron, perusahaan JV Foxconn dan Yulon, mengumumkan kerja sama dengan Nidec untuk memperkuat kekuatan dalam pengembangan komponen utama kendaraan listrik.
Pada Juli 2021, Foxconn bekerja sama dengan CTBC Financial Holding Co, Ltd untuk membuat dana baru yang menargetkan investasi EV. Pada bulan Juni 2021, Foxconn menginvestasikan T$995,2 juta ($36 juta) di Gigasolar Materials Corp untuk mengembangkan bahan baterai EV. Pada September 2021, Foxconn berkolaborasi dengan pemasok minyak milik negara Thailand, PTT Public Co. untuk menginvestasikan 1-2 miliar dolar AS dalam meluncurkan perusahaan patungan EV di Thailand. Di bulan yang sama, Foxconn dan Gogoro membentuk kemitraan teknologi dan manufaktur strategis untuk memperkenalkan tingkat kemampuan dan skala manufaktur baru untuk teknologi penukaran baterai Gogoro dan Skuter Pintar. Pada bulan Oktober 2021, mereka setuju untuk membeli bekas pabrik mobil GM dari Lordstown Motors dan membeli $50 juta saham biasa perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Foxconn akan menggunakan pabrik tersebut untuk memproduksi truk pikap Endurance milik Lordstown. Kendaraan Fisker juga akan dibuat di pabrik yang sama.
Pada bulan Januari 2022, Foxconn menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Penanaman Modal/BKPM, IBC, Indika, dan Gogoro untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem energi baru yang berkelanjutan di Indonesia yang berfokus pada baterai listrik, mobilitas listrik, dan industri terkait. Pada bulan Mei 2022, Foxconn mengumumkan penyelesaian pembelian fasilitas Lordstown Motors dan selanjutnya menandatangani perjanjian kontrak manufaktur dan perjanjian usaha patungan dengan LMC untuk pengembangan produk.
Pada pertengahan tahun 2021, Foxconn mengumumkan bahwa perusahaan akan memasuki lebih banyak produksi semikonduktor dan akan berekspansi untuk memasok chip untuk kendaraan listrik (EV) dan peralatan elektronik yang digunakan untuk perawatan kesehatan. Pada Mei 2021, Foxconn dan Yageo Group menandatangani perjanjian usaha patungan untuk membentuk XSemi Corporation ("XSemi") guna memperluas bisnis ke industri semikonduktor, termasuk pengembangan dan penjualan produk. Berbasis di Hsinchu, Taiwan, XSemi bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan sumber daya dari dua pemimpin pasar, selain kolaborasi beragam yang akan datang dengan perusahaan semikonduktor terkemuka dalam desain produk, proses dan perencanaan kapasitas, serta saluran penjualan. Pada Agustus 2021, Foxconn mengakuisisi Macronix Wafer Fab 6 inci seharga US$90,8 juta.
Pada Februari 2022, Foxconn membentuk perusahaan patungan dengan Vedanta Limited, salah satu grup multinasional terkemuka di India, untuk memproduksi semikonduktor di India. Foxconn keluar dari kesepakatan tersebut pada Juli 2023. Pada bulan April 2022, diumumkan bahwa Foxconn telah mengakuisisi perusahaan telekomunikasi nirkabel, arQana Technologies - dengan organisasi baru yang diganti namanya menjadi "iCana". Foxconn juga mengumumkan merger dengan perusahaan perancang sirkuit terpadu AchernarTek dengan nilai yang tidak disebutkan. Akuisisi dan konsolidasi ini akan membantu Foxconn mengembangkan semikonduktor untuk sektor otomotif dan infrastruktur 5G. Pada bulan September 2022, Foxtron, divisi otomotif Foxconn bekerja sama dengan Luxgen untuk meluncurkan kendaraan listrik pertamanya, Luxgen n7.
Operasi internasional
Foxconn memiliki 137 kampus dan kantor di 24 negara dan wilayah di seluruh dunia. Mayoritas pabrik Foxconn berlokasi di Asia Timur, dan yang lainnya di Brasil, India, Eropa, dan Meksiko.
Tiongkok Daratan
Foxconn memiliki 12 pabrik di sembilan kota di daratan Tiongkok-lebih banyak dari negara lain.
Pabrik Foxconn terbesar terletak di Kecamatan Longhua, Shenzhen, di mana ratusan ribu pekerja (dengan jumlah yang berbeda-beda termasuk 230.000, 300.000, dan 450.000) dipekerjakan di Longhua Science & Technology Park, sebuah kampus bertembok yang kadang-kadang disebut sebagai "Kota Foxconn".
Dengan luas sekitar 3 km2 (1,2 mil persegi), taman ini memiliki 15 pabrik, asrama pekerja, empat kolam renang, pemadam kebakaran, jaringan televisi sendiri (Foxconn TV), pusat kota dengan toko kelontong, bank, restoran, toko buku, dan rumah sakit. Sementara beberapa pekerja tinggal di kota-kota dan desa-desa di sekitarnya, yang lain tinggal dan bekerja di dalam kompleks; seperempat karyawan tinggal di asrama.
"Kota" pabrik Foxconn lainnya terletak di Zhengzhou Technology Park di Zhengzhou, provinsi Henan, di mana dilaporkan ada 120.000 pekerja yang dipekerjakan pada tahun 2012, kemudian, 200.000 pekerja dipekerjakan pada November 2022. Taman ini memproduksi sebagian besar lini iPhone Apple dan kadang-kadang disebut sebagai "Kota iPhone".
Ekspansi Foxconn di masa depan meliputi lokasi di Wuhan di provinsi Hubei, Kunshan di provinsi Jiangsu, Tianjin, Beijing, Huizhou, dan Guangzhou di provinsi Guangdong, Cina. Cabang Foxconn yang terutama memproduksi produk Apple adalah Hongfujin.
Pada tanggal 25 Mei 2016, BBC melaporkan bahwa Foxconn mengganti 60.000 karyawan karena telah mengotomatisasi "banyak tugas manufaktur yang terkait dengan operasi mereka". Organisasi ini kemudian mengkonfirmasi klaim tersebut.
Pada Juli 2021, banjir Henan melanda pabrik perakitan Apple iPhone terbesar di dunia di Zhengzhou, tetapi produksi tidak terpengaruh.
Pada 21 Oktober 2022, dan sebagai tanggapan atas wabah Covid di Zhengzhou Technology Park, Foxconn memberlakukan pembatasan pada pabrik perakitan iPhone-nya, dengan fasilitas makan di tempat ditutup. Pada tanggal 31 Oktober 2022, setelah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengendalikan wabah Covid mencegah pekerja meninggalkan kompleks, banyak pekerja yang melompati pagar untuk melarikan diri. Pada tanggal 2 November 2022, pemerintah memberlakukan penguncian ke Zona Ekonomi Bandara Zhengzhou, tempat pabrik Foxconn berada. Pada tanggal 23 November, para pekerja bentrok dengan penegak hukum terkait pembatasan COVID yang keras dan klaim bahwa Foxconn gagal memberikan paket gaji yang dijanjikan kepada karyawan baru. Video-video yang beredar di media sosial Tiongkok menggambarkan penegak hukum memukuli para pekerja yang memprotes serta kerumunan besar pekerja yang melawan penegak hukum.
Brasil
Semua fasilitas perusahaan di Amerika Selatan berlokasi di Brasil, dan ini termasuk pabrik ponsel di Manaus dan Indaiatuba serta basis produksi di Jundiaí, Sorocaba, dan Santa Rita do Sapucaí. Perusahaan sedang mempertimbangkan investasi lebih lanjut di Brasil.
Eropa
Foxconn memiliki pabrik di Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Pada tahun 2011, perusahaan ini merupakan eksportir terbesar kedua di Republik Ceko.
India
Pada awal tahun 2015, Foxconn telah bekerja sama dengan Sony untuk memproduksi televisi mereka dan menjualnya di seluruh India. Oleh karena itu, mereka memulai sebuah pabrik baru yang disebut Competition Team Technology (India) Private Limited di Irungattukottai (dekat Poonamallee, Chennai) yang kemudian dipindahkan ke Oragadam (Kanchipuram) pada tahun 2019. Pada pertengahan 2015, Foxconn sedang dalam pembicaraan untuk memproduksi iPhone Apple di India. Pada tahun 2015, Foxconn mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan dua belas pabrik di India dan akan menciptakan sekitar satu juta pekerjaan. Perusahaan ini juga mendiskusikan niatnya untuk bekerja sama dengan Grup Adani untuk ekspansi di negara ini. Pada bulan Agustus 2015, Foxconn berinvestasi di Snapdeal. Pada bulan September 2016, Foxconn mulai memproduksi produk dengan Gionee. Pada tahun 2017, Foxconn memulai produksi iPhone di Sriperumbudur, dekat Chennai. Pada bulan April 2019, Foxconn melaporkan bahwa mereka siap untuk memproduksi iPhone terbaru secara massal di India. Pimpinannya, Terry Gou, mengatakan bahwa produksi akan dilakukan di kota selatan Chennai. Pada bulan September 2022, Foxconn menandatangani kesepakatan untuk pabrik semikonduktor di Gujarat dengan investasi sebesar $21 miliar, oleh Vedanta Group. Pada bulan Juli 2023, Foxconn membuat keputusan untuk keluar dari proyek tersebut, dengan alasan sejumlah masalah dengan Vedanta Group dan juga masalah eksternal. Pada bulan Agustus 2023, selama pertemuan tahunannya, Foxconn dilaporkan menyatakan bahwa India saat ini menyumbang lebih dari 5% dari bisnis perusahaan dan ada banyak ruang untuk investasi di masa depan. Foxconn telah menetapkan target untuk mempekerjakan 2 juta orang dan memenuhi target India untuk mengekspor ponsel senilai 10 miliar dolar AS pada tahun 2030. Untuk memenuhi target ini, pada September 2023, perusahaan ini memiliki tiga pabrik manufaktur yang sedang dibangun, semuanya di India selatan-pabrik komponen dan semikonduktor di dekat pabrik perusahaan yang sudah ada di Chennai, dan dua pabrik di Bangalore (dekat bandara) dan Hyderabad (Kongara Kalan) untuk memproduksi iPhone, iPad, iPod, dan AirPod. Ketiga pabrik tersebut diproyeksikan akan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024. Ketiga pabrik ini akan mempekerjakan sekitar 400.000 orang dalam lima tahun pertama operasinya. Pada bulan November 2023, Foxconn mengumumkan investasi senilai 1,54 miliar dolar AS di India untuk "membantu memenuhi 'kebutuhan operasional'."
Jepang
Foxconn dan Sharp Corporation bersama-sama mengoperasikan dua pabrik yang mengkhususkan diri pada televisi layar lebar di Sakai, Osaka. Pada bulan Agustus 2012, dilaporkan bahwa Sharp, ketika melakukan restrukturisasi dan perampingan perusahaan, sedang mempertimbangkan untuk menjual pabrik-pabrik tersebut kepada Foxconn. Perusahaan ini diyakini akan menerima rencana tersebut. Akuisisi ini diselesaikan dengan kesepakatan senilai $3,8 miliar pada bulan Agustus 2016.
Malaysia
Pada tahun 2011, Foxconn memiliki setidaknya tujuh pabrik di negara bagian Johor, di Kulai, di mana perusahaan ini mengembangkan sebuah kawasan industri yang mencakup empat pabrik yang terdiri dari jalur perakitan otomatis serta jalur pengemasan otomatis.
Meksiko
Foxconn memiliki fasilitas di San Jerónimo, Chihuahua yang merakit komputer, dan dua fasilitas di Juárez - bekas basis produksi Motorola yang memproduksi ponsel, dan pabrik set-top box yang diakuisisi dari Cisco Systems. Televisi LCD juga dibuat di negara ini di Tijuana di pabrik yang diakuisisi dari Sony.
Pada tanggal 2 Juni 2022, Foxconn mengumumkan bahwa pabrik produksi mereka yang berbasis di Meksiko telah terkena serangan ransomware pada akhir Mei, sehingga mengganggu produksi. Fasilitas yang terkena dampak terletak di Tijuana, Baja California dan berspesialisasi dalam produksi elektronik konsumen, perangkat medis, dan produk industri.
Korea Selatan
Perusahaan ini menginvestasikan $377 juta pada bulan Juni 2014 untuk mengambil 4,9 persen kepemilikan saham di penyedia layanan TI Korea Selatan, SK C&C.
Amerika Serikat
Foxconn mengumumkan pada tanggal 26 Juli 2017 bahwa mereka akan membangun pabrik TV senilai $10 miliar di tenggara Wisconsin dan pada awalnya akan mempekerjakan 3.000 pekerja (yang akan meningkat menjadi 13.000). Sebagai bagian dari perjanjian, Foxconn akan menerima subsidi mulai dari $3 miliar hingga $4,8 miliar (dibayarkan secara bertahap jika Foxconn memenuhi target tertentu), yang sejauh ini merupakan subsidi terbesar yang pernah diberikan kepada perusahaan asing dalam sejarah AS. Beberapa pihak memperkirakan bahwa Foxconn diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar $51,5 miliar terhadap PDB Wisconsin selama 15 tahun ke depan, yaitu sebesar $3,4 miliar per tahun. Namun, banyak ekonom juga menyatakan skeptis bahwa manfaatnya akan melebihi biaya kesepakatan tersebut. Pihak lain telah mencatat bahwa Foxconn telah membuat klaim serupa tentang penciptaan lapangan kerja di masa lalu yang tidak membuahkan hasil.
Foxconn juga dibebaskan oleh Gubernur Scott Walker dari kewajiban mengajukan pernyataan dampak lingkungan, yang memicu kritik dari para pencinta lingkungan. Pabrik ini diperkirakan berkontribusi secara signifikan terhadap polusi udara di wilayah tersebut. Para pencinta lingkungan mengkritik keputusan untuk mengizinkan Foxconn mengambil 26.000 meter kubik (7×106 gal AS) air per hari dari Danau Michigan. Karena masalah air, Foxconn menghabiskan $30 juta untuk teknologi pembuangan cairan nol. Foxconn juga diharuskan untuk mengganti lahan basah dengan rasio yang lebih tinggi daripada perusahaan lain; Foxconn harus memulihkan 2 hektar lahan basah untuk setiap 1 hektar yang terganggu, bukan rasio 1,2 banding 1 untuk perusahaan lain.
Pada tanggal 4 Oktober 2017, Foxconn setuju untuk menempatkan pabrik mereka di Mount Pleasant, Wisconsin, dan melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 28 Juni 2018. Presiden Trump hadir untuk mempromosikan manufaktur Amerika.
Pada Januari 2019, Foxconn mengatakan sedang mempertimbangkan kembali rencana awalnya untuk memproduksi layar LCD di pabrik Wisconsin, dengan alasan biaya tenaga kerja yang tinggi di Amerika Serikat.
Di bawah perjanjian baru yang diumumkan pada April 2021, Foxconn akan mengurangi investasi yang direncanakan menjadi $672 juta dengan 1.454 pekerjaan baru. Kredit pajak yang tersedia untuk proyek tersebut dikurangi menjadi $8 juta.
Pada Oktober 2021, Lordstown Motors mengumumkan kesepakatan senilai $250 juta untuk menjual bekas pabrik GM ke Foxconn, yang akan menjadi perakit kontrak untuk truk pickup Endurance milik perusahaan. Kesepakatan tersebut diselesaikan pada Mei 2022 dengan harga akhir sebesar $ 230 juta. Foxconn juga mengumumkan akan menginvestasikan 50 juta dolar AS ke dalam perusahaan melalui pembelian saham biasa.
Disadur dari : en.wikipedia.org
Teknik Industri
Apa Siklus Hidup Pengembangan Produk?
Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025
Ide dan barang memiliki siklus hidup, seperti halnya manusia dan makhluk lainnya. Dari percikan awal sebuah ide, penciptaan inovasi baru, hingga akhirnya mati. Berbagai tahap perjalanan ini masing-masing menawarkan peluang dan tantangan uniknya sendiri. Selain itu, setiap produk memiliki jalan yang berbeda, seperti halnya setiap narasi kehidupan.
Namun, bagaimana jika kita dapat mengungkap tema-tema yang ada di sepanjang perjalanan ini? Bagaimana jika kita dapat memahami rencana yang mengatur siklus hidup setiap produk? Dalam artikel ini, kita akan membahas Siklus Hidup Pengembangan Produk (PDLC). Siklus Hidup Pengembangan Produk paling baik didefinisikan sebagai peta jalan terperinci untuk meluncurkan produk atau layanan baru.
Kita akan melihat tindakan utama, kesulitan, dan praktik terbaik yang terkait dengan setiap tahap perjalanan ini, mulai dari Pembuatan Ide hingga Komersialisasi. Kami akan memeriksa lebih dekat variabel-variabel yang mungkin berpengaruh pada proses pengembangan produk serta metode yang dapat digunakan bisnis untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Oleh karena itu, artikel ini cocok untuk Anda jika Anda seorang pengusaha, pemasar, atau pemilik bisnis.
Siklus hidup pengembangan produk tradisional
Siklus Hidup Pengembangan Produk (PDLC) tradisional adalah prosedur terorganisir yang menjelaskan proses yang diperlukan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Ini adalah panduan langkah demi langkah yang membantu perusahaan dalam mengenali dan mengendalikan beberapa fase pengembangan produk, mulai dari pembuatan ide pertama hingga komersialisasi produk.
Siklus Hidup Pengembangan Produk adalah proses siklus, oleh karena itu dimulai kembali dengan pengenalan barang atau jasa baru setelah produk mencapai akhir masa manfaatnya. Ini adalah alat yang penting untuk mengembangkan produk yang efektif yang memuaskan keinginan konsumen. Siklus Hidup Pengembangan Produk (PDLC) membantu perusahaan dalam mengidentifikasi prospek barang atau jasa baru, menilai kelayakan produk, merancang dan mengembangkan produk, menguji dan memvalidasinya, dan pada akhirnya meluncurkannya ke pasar.
PDLC adalah alat yang sangat baik untuk perusahaan karena memastikan bahwa barang dikembangkan secara efektif dan efisien. PDLC memungkinkan perusahaan mengenali dan mengontrol banyak tahap pengembangan produk, yang bisa jadi sulit dan memakan waktu. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka membuat penilaian yang tepat di setiap tingkat proses pengembangan produk dengan mengikuti pendekatan yang telah ditentukan.
Sangat penting untuk diingat bahwa Siklus Hidup Pengembangan Produk (PDLC) adalah kerangka kerja yang luas, sehingga dapat berubah tergantung pada bisnis atau produk. Bisnis dapat memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi unik mereka. Konsep keseluruhannya adalah menciptakan proses terorganisir yang membantu memasarkan produk dengan cara yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan misi perusahaan, tren pasar, dan kebutuhan konsumen.
Berikut adalah lima tahap utama dalam Siklus Hidup Pengembangan Produk. Mari kita lihat setiap tahap secara mendetail.
Generasi Ide
Langkah pertama dari Product Development Life Cycle (PDLC), yaitu Idea Generation, adalah di mana perusahaan menghasilkan konsep baru yang inovatif untuk barang atau jasa. Menemukan prospek untuk barang atau jasa baru yang akan memuaskan keinginan konsumen dan menghasilkan uang untuk bisnis adalah tujuan dari fase ini.
Bisnis melakukan riset pasar untuk memahami persyaratan dan preferensi target pasar mereka selama proses penciptaan ide. Melalui kuesioner, kelompok fokus, dan wawancara, mereka memperoleh masukan dari pelanggan. Mereka juga menilai tren pasar dan mencari peluang di mana barang atau jasa baru diperlukan. Mereka mungkin juga mencermati prosedur internal mereka sendiri untuk menemukan area di mana peningkatan efisiensi atau potensi perbaikan dapat direalisasikan.
Selama tahap ini, berbagai teknik digunakan untuk mengembangkan sejumlah besar ide, termasuk sesi curah pendapat, lokakarya inovasi, dan kompetisi ide. Perusahaan juga menggunakan berbagai metodologi untuk menilai kelayakan setiap ide, termasuk analisis SWOT, analisis PESTLE, dan Lima Kekuatan Porter.
Ide-ide tersebut kemudian diprioritaskan dan dievaluasi berdasarkan seberapa besar kemungkinan ide tersebut berhasil. Dalam proses penilaian, variabel seperti kelayakan teknologi, potensi komersial, dan kelayakan finansial diperhitungkan. Konsep yang paling menjanjikan akan maju ke tahap berikutnya, yaitu pengembangan konsep.
Tahap Pembuatan Ide sangat penting karena meletakkan dasar untuk seluruh prosedur pengembangan produk. Kualitas dan relevansi konsep yang dibuat selama tahap ini menentukan keberhasilan produk. Untuk menjamin bahwa mereka menghasilkan ide terbaik dan memiliki dasar yang kuat untuk tahap-tahap selanjutnya dalam proses pengembangan produk, sangat penting bagi perusahaan untuk mencurahkan waktu dan sumber daya pada tahap ini.
Pengembangan konsep
Langkah kedua dari siklus hidup pengembangan produk (PDLC), yang dikenal sebagai pengembangan konsep, adalah di mana perusahaan mulai mengembangkan dan menyempurnakan konsep yang telah dikembangkan pada fase pertama. Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang produk atau layanan yang dimaksud serta pasar prospektifnya.
Perusahaan melakukan riset pasar lebih lanjut selama fase pengembangan konsep untuk memastikan kelangsungan ide dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang target pasar dan persaingan. Selain itu, mereka menilai kelayakan teknis produk, mencari potensi hambatan, dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk.
Bisnis menganalisis konsep produk dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk Studi Kelayakan, Kanvas Proposisi Nilai, dan Kanvas Model Bisnis". Selain itu, mereka mengevaluasi konsep produk dan mendapatkan masukan dari klien dengan menggunakan pendekatan simulasi dan pembuatan prototipe.
Bisnis juga membuat spesifikasi produk yang merinci fitur, fungsionalitas, dan desain produk setelah konsep produk terbukti. Selain itu, mereka juga membuat kasus bisnis yang menjelaskan biaya produk, target pasar, dan aliran pendapatan prospektif.
Sebelum mengerahkan sumber daya yang besar untuk tahap desain dan pengembangan, tahap Pengembangan Konsep sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk menilai kelayakan produk dan mengidentifikasi hambatan potensial. Selain itu, tahap ini juga membantu dalam mengidentifikasi target pasar, kompetisi, dan proposisi nilai untuk produk. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka menciptakan produk yang memiliki potensi untuk sukses di pasar dengan meluangkan waktu untuk menilai konsep produk dengan cermat.
Desain dan pengembangan
Tahap ketiga dari siklus hidup pengembangan produk (PDLC), yang dikenal sebagai "Desain dan Pengembangan", adalah ketika organisasi merancang dan membangun barang atau jasa menggunakan data yang diperoleh pada tahap lainnya. Membuat prototipe produk yang dapat diuji dan disetujui sebelum dipasarkan adalah tujuan dari tahap ini.
Perusahaan berkolaborasi dengan sekelompok profesional, termasuk insinyur, desainer, dan pengembang perangkat lunak, selama fase Desain dan Pengembangan untuk menghasilkan prototipe produk yang berfungsi. Untuk menciptakan produk yang berguna dan menarik secara visual, mereka menggunakan berbagai alat dan metode, termasuk perangkat lunak desain berbantuan komputer (CAD), pemodelan 3D dan perangkat lunak simulasi, serta praktik pengembangan yang gesit.
Selama fase ini, perusahaan menguji dan memvalidasi produk untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan pada fase sebelumnya. Mereka meminta umpan balik dari klien dan pemangku kepentingan sambil menguji produk untuk kegunaan, kinerja, dan fungsionalitas.
Perusahaan menyediakan dokumentasi teknis menyeluruh yang merinci produk, fitur-fiturnya, dan cara pengoperasiannya setelah melalui pengembangan dan pengujian menyeluruh. Selain itu, mereka juga membuat panduan pengguna dan materi lain yang akan digunakan untuk mendukung produk setelah dipasarkan.
Langkah Desain dan Pengembangan, yang melibatkan pembuatan produk nyata dan merupakan tahap yang paling memakan waktu dan sumber daya yang intensif, sangat penting. Untuk menjamin bahwa produk dikembangkan sesuai jadwal, sesuai anggaran, dan sesuai dengan standar kualitas yang diperlukan, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana yang jelas dan proses yang jelas. Perusahaan dapat memastikan bahwa produk berhasil setelah dikirim ke pasar dengan melakukan pengujian dan validasi secara ekstensif untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan target pasar.
Komersialisasi
Siklus Hidup Pengembangan Produk (PDLC) yang ideal diakhiri dengan tahap Komersialisasi, di mana perusahaan memperkenalkan barang atau jasa mereka ke pasar dan mulai menghasilkan uang. Namun, penting untuk dicatat bahwa tahap komersialisasi tidak selalu berarti akhir dari siklus hidup produk; itu mungkin berlanjut melalui tahap penurunan.
Membuat produk atau layanan dapat diakses oleh target pasar dan menghasilkan pendapatan untuk bisnis adalah tujuan dari fase komersialisasi. Bisnis membuat dan menerapkan strategi pemasaran dan promosi untuk produk selama fase komersialisasi. Untuk menjelaskan karakteristik dan keunggulan produk kepada pembeli, mereka menyediakan materi pemasaran seperti brosur, selebaran, dan video. Untuk menentukan cara terbaik untuk menghubungi target pasar, mereka juga melakukan riset pasar, menggunakan alat seperti media sosial, email, atau iklan berbayar.
Seiring dengan penetapan harga, pengemasan, dan logistik, bisnis juga menetapkan strategi distribusi dan penjualan untuk produk mereka. Untuk membantu klien dengan pertanyaan atau masalah apa pun yang mungkin mereka hadapi dengan produk, mereka juga membuat sistem layanan pelanggan dan dukungan.
Bisnis secara aktif memantau kinerja produk setelah diperkenalkan ke pasar dengan menggunakan indikator yang mencakup penjualan, umpan balik pelanggan, dan pangsa pasar. Untuk meningkatkan produk dan menemukan potensi pengembangan produk di masa depan, mereka juga mengumpulkan umpan balik dari klien.
Tahap komersialisasi dapat dibagi menjadi tiga tahap:
Tahap pengenalan
Produk atau layanan baru pertama kali diperkenalkan ke pasar selama tahap Pengenalan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan penjualan awal, mengumpulkan umpan balik dari konsumen, dan meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk.
Biasanya, sejumlah kecil pengadopsi awal, seperti penguji beta atau sekelompok konsumen tertentu, diperkenalkan ke produk selama tahap ini. Sebelum merilis produk ke audiens yang lebih besar, perusahaan mempekerjakan kelompok ini untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk, perusahaan juga sangat menekankan pada pengembangan strategi pemasaran yang efisien dan jaringan distribusi yang solid.
Penjualan yang rendah dan biaya pemasaran dan distribusi yang besar menentukan periode ini. Bisnis ini mengeluarkan uang untuk pengenalan merek dan akuisisi pelanggan, yang dapat mengakibatkan biaya yang besar. Untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, perusahaan harus mengelola biaya dengan hati-hati selama fase ini.
Karena tahap ini menjadi dasar bagi kesuksesan produk di masa depan, tahap pengenalan adalah tahap yang sangat penting dalam proses pengembangan produk. Apakah sebuah produk akan sukses dalam jangka panjang dapat disimpulkan dari seberapa baik produk tersebut diterima pada awalnya dan dari umpan balik konsumen. Penjualan awal yang kuat dan umpan balik pelanggan yang baik dari tahap pengenalan yang dilakukan dengan baik dapat membantu memantapkan produk di pasar dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan di masa depan.
Tahap pertumbuhan
Fase di mana produk dapat diterima di pasar dan penjualan mulai meningkat dikenal sebagai tahap Pertumbuhan. Meningkatkan pangsa pasar dan memperluas basis konsumen adalah tujuan dari tahap ini.
Untuk menjangkau audiens yang lebih besar, perusahaan sekarang berkonsentrasi pada pengembangan jaringan distribusi dan inisiatif pemasaran. Selain itu, bisnis ini berusaha untuk menjalin hubungan dengan klien dan rekanan bisnis yang signifikan. Perusahaan juga dapat mengeluarkan uang untuk penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk atau menambahkan fitur baru.
Penjualan meningkat selama fase ini sementara biaya pemasaran dan distribusi turun. Bisnis dapat mulai berkonsentrasi pada manajemen biaya dan efisiensi ketika produk menemukan pasar. Pengembalian investasi awal perusahaan yang dilakukan selama tahap pengenalan juga dapat ditunjukkan.
Tahap pertumbuhan ini menetapkan produk di pasar dan meletakkan dasar untuk profitabilitas di masa depan. Ini adalah tahap yang sangat penting dalam proses pengembangan produk. Keberhasilan jangka panjang produk mungkin bergantung pada kapasitas perusahaan untuk mengembangkan basis klien dan pangsa pasar selama fase ini. Secara keseluruhan, tahap pertumbuhan yang kuat dapat menghasilkan peningkatan pendapatan, pangsa pasar yang lebih besar, dan posisi yang lebih mapan di pasar.
Tahap kedewasaan
Tahap Kematangan adalah fase berikutnya dalam tahap komersialisasi. Dalam hal penjualan dan pangsa pasar, ini adalah titik di mana produk mencapai puncaknya. Akibat kejenuhan pasar, penjualan mulai mendatar. Mempertahankan pangsa pasar dan memaksimalkan pendapatan adalah tujuan dari fase ini.
Perusahaan berkonsentrasi untuk mempertahankan pelanggan saat ini dan meningkatkan produktivitas pada titik ini. Untuk meningkatkan profitabilitas, mereka mungkin juga bekerja pada manajemen biaya dan strategi penetapan harga. Untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya, perusahaan juga sangat menekankan pada pengembangan produk, meningkatkan atau menambahkan fitur baru pada produk yang sudah ada.
Penjualan pada saat ini konsisten, dan hanya ada sedikit ruang untuk pengembangan. Ketika pasar produk menjadi jenuh, meningkatkan penjualan menjadi lebih menantang. Mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dengan memangkas biaya menjadi prioritas utama perusahaan.
Tahap kedewasaan, yang menandai berakhirnya fase pertumbuhan produk dan dimulainya tahap penurunan, merupakan tahap penting dalam proses pengembangan. Membuat keputusan strategis tentang masa depan produk selama tahap kritis ini akan membantu perusahaan menentukan kinerja produk dan potensi masa depan. Tahap kedewasaan yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan profitabilitas produk yang berkelanjutan dan posisi pasar yang stabil.
Singkatnya, tahap Komersialisasi dapat diibaratkan sebagai bagian dari kisah epik perjalanan sebuah produk, di mana semua kerja keras dan dedikasi dari tahap-tahap sebelumnya membuahkan hasil. Ini adalah momen ketika tirai dibuka dan lampu sorot menyoroti produk, siap untuk naik ke atas panggung dan memukau para pendengarnya. Namun, ini adalah fase yang krusial karena menentukan keberhasilan produk dan laba atas investasi perusahaan. Dengan meluncurkan produk secara efektif dan menghasilkan pendapatan, bisnis dapat memastikan kesuksesan dan profitabilitas produk yang berkelanjutan.
Penurunan
Tahap Penurunan adalah tahap akhir dari Siklus Hidup Pengembangan Produk (PDLC) dan merupakan tahap di mana penjualan dan pangsa pasar produk mulai menurun. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengontrol penghentian produk dan mengurangi kerugian bagi perusahaan.
Perusahaan mulai mengurangi investasinya pada produk selama tahap penurunan, misalnya dengan mengurangi biaya pemasaran dan iklan. Selain itu, perusahaan mulai mengurangi produksi dan bahkan dapat berhenti membuat produk sepenuhnya. Selain itu, perusahaan dapat berkonsentrasi untuk membantu dan melayani klien saat ini serta menjual barang yang tersisa.
Penjualan dan profitabilitas menurun pada tahap ini. Tidak ada lagi permintaan yang cukup untuk produk untuk mendukung produksi karena pasar telah jenuh. Pada titik ini, prioritas utama perusahaan adalah membatasi kerugian dan mengembalikan investasi awal sebanyak mungkin.
Selama tahap ini, penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana untuk mengelola penurunan produk, karena hal ini dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tahap penurunan produk yang dikelola dengan baik dapat membantu perusahaan memulihkan sebanyak mungkin investasinya dan meminimalkan kerugian.
Melampaui batas akhir: masa pakai produk yang mengejutkan
Akhir dari siklus hidup suatu produk tidak selalu berarti kematian langsung atau menghilang sama sekali dari pasar. Beberapa produk menghilang dengan tenang menuju matahari terbenam, sementara yang lain membuat comeback yang hebat, menentang segala rintangan.
Berikut adalah beberapa skenario akhir yang mungkin terjadi pada sebuah produk:
Kematian bertahap
Dalam skenario ini, penjualan dan pangsa pasar produk secara bertahap menurun dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya mengarah pada penghentian produk tersebut. Ilustrasi konkret dari hal ini adalah kamera film Kodak. Kebutuhan akan kamera film dengan cepat berkurang seiring dengan berkembangnya kamera digital, yang mengakibatkan lini produk kamera film Kodak dihentikan.
Kematian segera
Skenario ini menggambarkan penghentian produk secara tiba-tiba, sering kali sebagai akibat dari pergeseran yang signifikan di pasar atau kurangnya permintaan. Ilustrasi yang bagus untuk hal ini adalah smartphone BlackBerry. Popularitas iPhone dan smartphone Android menyebabkan penurunan dramatis dalam permintaan untuk BlackBerry, yang pada akhirnya menyebabkan produk ini dihentikan.
Turun-temurun melalui Transformasi
Dalam hal ini, sebuah produk mengalami transformasi menjadi produk baru dengan tetap mempertahankan beberapa atribut sebelumnya. Nintendo Gameboy, yang berevolusi menjadi Nintendo DS dan kemudian Nintendo 3DS, berfungsi sebagai ilustrasi untuk hal ini.
Inspirasi
Dalam hal ini, kita berbicara tentang produk yang memberikan ide untuk pengembangan di masa depan. Sebuah produk dapat menjadi inspirasi untuk barang atau jasa baru dalam dua cara: secara positif, seperti dalam kasus Apple iPhone, yang memengaruhi desain banyak ponsel pintar, atau secara negatif, seperti dalam kasus Ford Pinto, yang ditarik kembali karena masalah keamanan dan mendorong pengembangan peraturan untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
Peninggalan
Dalam kasus ini, sebuah produk digambarkan sebagai barang budaya atau barang bersejarah, sering kali karena sentimentalitas atau nostalgia. Volkswagen Beetle, yang masih disukai oleh para penggemar mobil dan dianggap sebagai ikon budaya, adalah salah satu contohnya.
Kebangkitan
Dalam skenario akhirat terakhir ini, sebuah produk yang telah ditarik dari pasar untuk sementara waktu, sekali lagi tersedia. Kamera instan Polaroid, yang dikembalikan ke pasar setelah dihentikan produksinya pada tahun 2008, adalah ilustrasi yang bagus untuk hal ini.
Faktor tak terduga yang dapat mengubah perjalanan produk
Kita telah membahas siklus hidup produk yang ideal. Namun, siklus hidup produk seperti naik rollercoaster, penuh dengan liku-liku, belokan, dan penurunan yang tidak terduga. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan kegembiraan dan antisipasi, tetapi juga perjalanan yang penuh dengan potensi jebakan.
Gangguan pada siklus hidup produk yang ideal dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa faktor paling umum yang memengaruhi siklus hidup pengembangan produk.
Faktor internal
Kurangnya sumber daya, seperti uang atau staf, atau kurangnya arah dan tujuan dalam organisasi adalah contoh faktor internal. Hal ini dapat menunda pengembangan dan peluncuran produk dan mungkin memaksa produk dihentikan.
Faktor eksternal
Perubahan di pasar, seperti pesaing baru yang masuk ke pasar atau pergeseran preferensi konsumen, merupakan contoh kekuatan eksternal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan, hilangnya pangsa pasar, atau bahkan keusangan suatu produk.
Kondisi ekonomi
Siklus hidup produk yang lancar juga dapat terhambat oleh faktor ekonomi seperti resesi atau kenaikan harga bahan baku. Pengeluaran konsumen dapat menurun sebagai akibat dari keadaan ini, yang akan mempersulit bisnis untuk tetap menguntungkan.
Kemajuan teknologi
Perkembangan teknologi, yang dapat membuat produk menjadi usang, adalah sumber gangguan lain yang mungkin terjadi. Misalnya, kamera film menjadi usang karena kamera digital menjadi lebih populer.
Masalah peraturan dan hukum
Siklus hidup suatu produk juga dapat dipengaruhi oleh kesulitan hukum dan peraturan. Misalnya, penarikan produk dapat mengakibatkan pemberitaan yang buruk dan penurunan penjualan.
Tembakan Perpisahan: Siklus Hidup Pengembangan Produk adalah Perjalanan Penciptaan, Pertumbuhan, dan (terkadang) Kebangkitan
Siklus Hidup Pengembangan Produk adalah kisah setua waktu, sebuah kisah tentang penciptaan, pertumbuhan, dan (terkadang) kebangkitan. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan kegembiraan dan tantangan, tetapi pada akhirnya, ini adalah perjalanan yang mengarah pada lahirnya sesuatu yang baru dan inovatif.
Jadi, ketika Anda memulai perjalanan pengembangan produk Anda sendiri, ingatlah bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan sedikit kreativitas, produk Anda pun dapat mencapai potensi penuhnya dan meninggalkan dampak yang langgeng bagi dunia.
Disadur dari: productledalliance.com
Agroteknologi & Teknologi Bioproduk
Mesin Traktor, Apa Saja Fungsinya?
Dipublikasikan oleh Anisa pada 28 Februari 2025
Traktor, sebuah ikon dalam mekanisasi pertanian, adalah kendaraan yang dirancang untuk menarik alat atau trailer dalam kegiatan konstruksi atau pertanian atau untuk melakukan traksi tinggi pada kecepatan rendah. Istilah ini digunakan secara luas untuk menggambarkan berbagai jenis kendaraan yang melayani fungsi ini. Traktor merupakan tulang punggung dalam mekanisasi pertanian, membantu menggerakkan instrumen pertanian, baik dengan menarik maupun mendorong, dan menjadi komponen utama dalam proses pertanian modern.
Asal-usul kata "traktor" dapat ditelusuri hingga ke kata Latin "trahere", yang berarti "menarik". Di samping itu, ada teori yang menyatakan bahwa kata "traktor" berasal dari frasa "traksi motor", yang merujuk pada "motor yang menarik". Istilah ini awalnya diciptakan untuk memperpendek definisi "mesin atau kendaraan yang menarik gerbong atau bajak" menjadi kata tunggal yang mudah dipahami.
Penggunaan kata "traktor" cenderung merujuk pada "traktor pertanian" di berbagai negara seperti Inggris, Irlandia, Australia, India, Spanyol, Argentina, dan Jerman. Namun, di Amerika Serikat dan Kanada, istilah ini lebih jarang digunakan untuk merujuk pada jenis kendaraan lainnya.
Penggunaan mesin uap untuk mengontrol instrumen mekanis pertanian adalah awal dari era mekanisasi pertanian pada abad ke-19. Sekitar tahun 1850, mesin penarik pertama dikembangkan dari teknologi ini dan segera menjadi komponen penting di bidang pertanian. Mesin bajak bermesin uap adalah contoh awal dari traktor pertama.
Traktor, kecuali traktor jalur, umumnya memiliki empat roda, dengan dua roda yang lebih besar di bagian belakang atau keempat roda berukuran sama. Traktor jalur memiliki penggerak mirip tank yang memungkinkannya bergerak di berbagai medan. Pada tahun 1930-an, traktor jalur mulai populer, terutama di California, karena kemampuannya menangani medan yang berat.
Awalnya, traktor dijalankan dengan mesin uap. Namun, pada awal abad ke-20, mesin pembakaran dalam mulai menjadi sumber tenaga utama untuk traktor. Dari sekitar tahun 1900 hingga 1960, bensin menjadi bahan bakar utama, meskipun etanol dan minyak tanah juga digunakan sebagai alternatif. Traktor pertanian modern umumnya menggunakan mesin diesel, dengan kekuatan bervariasi antara 18 hingga 575 tenaga kuda (15 hingga 480 kW), dan dieselisasi mencapai puncaknya pada tahun 1960-an.
Traktor telah menjadi tonggak penting dalam revolusi pertanian modern, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan skala operasi di bidang pertanian. Dengan terus berkembangnya teknologi dan desain, traktor terus menjadi bagian integral dari evolusi pertanian global, membantu petani di seluruh dunia menghadapi tantangan dan tuntutan produksi pangan yang terus berkembang.
Sumber:
Teknik Industri
Manajemen Ilmiah
Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025
Manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang menganalisis dan mensintesis alur kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktivitas tenaga kerja. Ini adalah salah satu upaya paling awal untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada rekayasa proses pada manajemen. Manajemen ilmiah kadang-kadang dikenal sebagai Taylorisme setelah pelopornya, Frederick Winslow Taylor.
Taylor memulai pengembangan teori ini di Amerika Serikat pada tahun 1880-an dan 1890-an dalam industri manufaktur, terutama baja. Puncak pengaruhnya terjadi pada tahun 1910-an. Meskipun Taylor meninggal pada tahun 1915, pada tahun 1920-an manajemen ilmiah masih berpengaruh tetapi telah memasuki persaingan dan sinkretisme dengan ide-ide yang berlawanan atau saling melengkapi.
Meskipun manajemen ilmiah sebagai teori atau aliran pemikiran yang berbeda telah usang pada tahun 1930-an, [klarifikasi diperlukan] sebagian besar temanya masih menjadi bagian penting dari teknik dan manajemen industri saat ini.
Tema-tema tersebut meliputi: analisis; sintesis; logika; rasionalitas; empirisme; etos kerja; efisiensi melalui penghapusan kegiatan yang boros (seperti dalam muda, muri, dan mura); standarisasi praktik-praktik terbaik; meremehkan tradisi yang dilestarikan hanya untuk kepentingannya sendiri atau untuk melindungi status sosial dari pekerja tertentu dengan keahlian tertentu; transformasi produksi kerajinan menjadi produksi massal; dan transfer pengetahuan antara pekerja dan dari pekerja ke dalam alat, proses, dan dokumentasi.
Nama
Nama yang diberikan Taylor untuk pendekatannya pada awalnya adalah “manajemen toko” dan “manajemen proses”. Namun, “manajemen ilmiah” menjadi perhatian nasional pada tahun 1910 ketika pengacara perang salib Louis Brandeis (yang saat itu belum menjadi hakim agung) mempopulerkan istilah tersebut.[3] Brandeis telah mencari istilah konsensus untuk pendekatan ini dengan bantuan praktisi seperti Henry L. Gantt dan Frank B. Gilbreth. Brandeis kemudian menggunakan konsensus “manajemen ilmiah” ketika dia berargumen di hadapan Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian (ICC) bahwa kenaikan tarif kereta api yang diusulkan tidak diperlukan meskipun terjadi peningkatan biaya tenaga kerja; dia menduga manajemen ilmiah akan mengatasi ketidakefisienan kereta api (ICC memutuskan untuk tidak menyetujui kenaikan tarif, tetapi juga menganggap tidak ada bukti yang cukup bahwa konsep tersebut tidak efisien). Taylor mengakui istilah “manajemen ilmiah” yang dikenal secara nasional sebagai nama lain yang bagus untuk konsep ini, dan mengadopsinya dalam judul monograf tahun 1911 yang berpengaruh.
Sejarah
Midvale Steel Company, “salah satu pabrik pembuat pelat baja terbesar di Amerika,” adalah tempat kelahiran manajemen ilmiah. Pada tahun 1877, Frederick W. Taylor mulai bekerja sebagai juru tulis di Midvale, namun naik jabatan menjadi mandor pada tahun 1880. Sebagai mandor, Taylor “selalu terkesan dengan kegagalan [anggota timnya] untuk menghasilkan lebih dari sepertiga dari [apa yang dia anggap] pekerjaan yang baik dalam sehari.
Taylor bertekad untuk menemukan, dengan metode ilmiah, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang untuk melakukan setiap pekerjaan yang diberikan; dan pada musim gugur tahun 1882 dia mulai menerapkan fitur pertama dari manajemen ilmiah ke dalam operasi.
Horace Bookwalter Drury, dalam karyanya pada tahun 1918, Scientific management: Sebuah Sejarah dan Kritik, mengidentifikasi tujuh pemimpin lain dalam gerakan ini, yang sebagian besar mempelajari dan memperluas manajemen ilmiah dari upaya Taylor:
- Henry L. Gantt (1861-1919)
- Carl G. Barth (1860-1939)
- Horace K. Hathaway (1878-1944)
- Morris L. Cooke (1872-1960)
- Sanford E. Thompson (1867-1949)
Frank B. Gilbreth (1868-1924). Karya independen Gilbreth tentang “studi gerak” tercatat sejak tahun 1885; setelah bertemu Taylor pada tahun 1906 dan diperkenalkan pada manajemen ilmiah, Gilbreth mengabdikan upayanya untuk memperkenalkan manajemen ilmiah ke dalam pabrik-pabrik. Gilbreth dan istrinya Lillian Moller Gilbreth (1878-1972) melakukan studi gerak mikro menggunakan kamera stop-motion serta mengembangkan profesi psikologi industri/organisasi.
Harrington Emerson (1853-1931) mulai menentukan produk dan biaya pabrik industri dibandingkan dengan yang seharusnya pada tahun 1895. Emerson tidak bertemu dengan Taylor hingga Desember 1900, dan keduanya tidak pernah bekerja sama.
Kesaksian Emerson pada akhir 1910 kepada Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian membuat gerakan ini menjadi perhatian nasional dan memicu pertentangan serius. Emerson berpendapat bahwa jalur kereta api dapat menghemat $1.000.000 per hari dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada efisiensi operasi. Pada bulan Januari 1911, sebuah jurnal perkeretaapian terkemuka memulai serangkaian artikel yang menyangkal bahwa kereta api dikelola secara tidak efisien.
Ketika langkah-langkah diambil untuk memperkenalkan manajemen ilmiah di Rock Island Arsenal milik pemerintah pada awal tahun 1911, hal ini ditentang oleh Samuel Gompers, pendiri dan Presiden Federasi Buruh Amerika (aliansi serikat pekerja). Ketika upaya berikutnya dilakukan untuk memperkenalkan sistem bonus ke dalam pengecoran Watertown Arsenal milik pemerintah selama musim panas 1911, seluruh pekerja melakukan aksi mogok kerja selama beberapa hari. Investigasi Kongres kemudian dilakukan, yang menghasilkan larangan penggunaan studi waktu dan membayar premi dalam layanan Pemerintah.
Kematian Taylor pada tahun 1915 di usia 59 tahun membuat gerakan ini tidak memiliki pemimpin aslinya. Dalam literatur manajemen saat ini, istilah “manajemen ilmiah” sebagian besar mengacu pada karya Taylor dan murid-muridnya (“klasik”, menyiratkan “tidak lagi mutakhir, tetapi masih dihormati karena nilai seminalnya”) yang berbeda dengan iterasi yang lebih baru dan lebih baik dari metode pencarian efisiensi. Saat ini, optimalisasi tugas yang berorientasi pada tugas kerja hampir ada di mana-mana di industri.
Prinsip-prinsip Manajemen Ilmiah
Frederick Taylor menghadapi tantangan untuk membuat bisnis menjadi produktif dan menguntungkan selama bertahun-tahun bekerja dan melakukan penelitian di perusahaan baja. Dia percaya pada solusi ilmiah. Dalam artikel “Manajemen Toko”, Taylor menjelaskan bahwa ada dua fakta yang muncul “paling penting” di bidang manajemen: (a) “Ketidakseragaman yang besar”: kurangnya keseragaman dalam apa yang disebut “manajemen”, (b) Kurangnya hubungan antara manajemen (toko) yang baik dengan upah. Dia menambahkan,
“Seni manajemen telah didefinisikan, ‘sebagai mengetahui dengan tepat apa yang Anda ingin orang lakukan, dan kemudian melihat bahwa mereka melakukannya dengan cara yang terbaik dan termurah’.
Dalam hal ini, ia menyoroti bahwa meskipun “tidak ada definisi yang ringkas” untuk seni ini, “hubungan antara majikan dan karyawan merupakan bagian terpenting dari seni ini”.
Dia kemudian melanjutkan bahwa manajemen yang baik dalam jangka panjang harus memberikan kepuasan bagi manajer dan pekerja. Taylor menekankan bahwa dia menganjurkan “upah tinggi” dan “biaya tenaga kerja rendah” sebagai “fondasi manajemen terbaik. Membahas upah untuk kelas pekerja yang berbeda dan apa yang disebutnya sebagai pekerja “kelas satu”, dia membandingkan berbagai skenario pengerjaan dan pro dan kontranya. Untuk manajemen terbaik, ia menegaskan dengan banyak alasan bahwa para manajer dalam sebuah organisasi harus mengikuti pedoman berikut ini:
- Setiap pekerja harus diberikan pekerjaan dengan tingkat tertinggi yang mereka mampu lakukan.
- Setiap pekerja harus dituntut untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja kelas satu dan berkembang.
- Ketika setiap pekerja bekerja dengan kecepatan pekerja kelas satu, mereka harus dibayar 30% hingga 100% di atas rata-rata kelas mereka.
Meskipun Taylor menyatakan bahwa pembagian “pembagian keuntungan yang adil” diperlukan dalam sebuah organisasi, ia percaya bahwa manajemen dapat menyatukan upah yang tinggi dengan biaya tenaga kerja yang rendah dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut:
- Tugas harian yang besar: Setiap pekerja dalam organisasi harus memiliki tugas yang jelas.
- Kondisi Standar: Setiap pekerja harus diberikan kondisi dan peralatan standar yang memungkinkannya untuk melaksanakan tugasnya.
- Bayaran yang tinggi untuk kesuksesan: Setiap pekerja harus diberi imbalan ketika dia menyelesaikan tugas mereka.
- Kerugian jika terjadi kegagalan: Ketika seorang pekerja gagal, dia harus tahu bahwa dia akan ikut menanggung kerugian.
Dalam Manajemen Ilmiah, tanggung jawab keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi tidak hanya berada di pundak para pekerja, seperti yang terjadi pada sistem manajemen lama. Menurut Manajemen Ilmiah, para manajer memikul separuh beban dengan bertanggung jawab untuk menjamin kondisi kerja yang tepat untuk kesejahteraan pekerja. Dalam bukunya “Principles of Scientific Management”, Taylor secara resmi memperkenalkan teori Manajemen Ilmiah yang telah diteliti secara metodis.
Meskipun dia menjelaskan detail Manajemen Ilmiah dalam karyanya, dia tidak memberikan definisi ringkasnya. Sesaat sebelum kematiannya, Taylor menyetujui ringkasan dan definisi Manajemen Ilmiah yang disiapkan Hoxie berikut ini:
“Manajemen Ilmiah adalah sebuah sistem yang dirancang oleh para insinyur industri dengan tujuan untuk melayani kepentingan bersama para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas melalui penghapusan pemborosan yang dapat dihindari, perbaikan proses dan metode produksi secara umum, serta distribusi produk yang adil dan ilmiah.
Taylor mengindikasikan bahwa Manajemen Ilmiah terdiri dari empat prinsip dasar:
- Pengembangan ilmu pengetahuan yang benar: Kita harus menganalisis secara ilmiah semua bagian dari suatu pekerjaan. Hal ini terdiri dari pemeriksaan elemen dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta mengukur waktu optimal untuk setiap tugas. Kita juga perlu mengetahui waktu kerja per hari untuk pekerja yang berkualitas.
- Pemilihan pekerja secara ilmiah: Orang yang paling cocok untuk pekerjaan itu dipilih.
- Pendidikan dan pelatihan ilmiah para pekerja: Ada pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antara manajer dan pekerja. Sementara para pekerja melakukan pekerjaan dengan kualitas dan pengerjaan yang baik, manajer bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pelatihan yang tepat bagi para pekerja.
- Kerja sama antara manajer dan pekerja: Kerja sama ilmiah antara manajer dan pekerja diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan berkualitas tinggi.
Ada berbagai alat yang memungkinkan kita untuk memenuhi prinsip-prinsip ini, seperti studi waktu dan gerakan, kepemimpinan fungsional, standarisasi alat dan gerakan pekerja untuk setiap jenis pekerjaan, instruksi yang jelas untuk pekerja, dan akuntansi biaya.
Ada banyak fitur, alat, dan metode lain yang dikembangkan dan direkomendasikan Taylor selama bekerja di pabrik baja dan penelitian, yang memiliki jejak di bidang lain, seperti akuntansi dan Teknik. Beberapa konsep, studi, dan temuannya telah menyebabkan revolusi intelektual dalam manajemen organisasi.
Taylor memberikan kontribusi pada berbagai bidang seperti pengukuran kerja, perencanaan dan kontrol produksi, desain proses, kontrol kualitas, ergonomi, dan rekayasa manusia.
Mengejar efisiensi ekonomi
Berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, manajemen ilmiah dibangun di atas pengejaran efisiensi ekonomi sebelumnya. Meskipun sudah ada sebelumnya dalam kebijaksanaan rakyat tentang penghematan, manajemen ilmiah lebih menyukai metode empiris untuk menentukan prosedur yang efisien daripada melanggengkan tradisi yang sudah mapan.
Oleh karena itu, hal ini diikuti oleh banyak penerus dalam ilmu pengetahuan terapan, termasuk studi waktu dan gerakan, Gerakan Efisiensi (yang merupakan gema budaya yang lebih luas dari dampak manajemen ilmiah terhadap manajer bisnis secara khusus), Fordisme, manajemen operasi, penelitian operasi, teknik industri, ilmu manajemen, teknik manufaktur, logistik, manajemen proses bisnis, rekayasa ulang proses bisnis, manufaktur ramping, dan Six Sigma. Terdapat kontinum yang mengalir yang menghubungkan manajemen ilmiah dengan bidang-bidang berikutnya, dan pendekatan yang berbeda sering kali menunjukkan tingkat kompatibilitas yang tinggi.
Taylor menolak anggapan, yang bersifat universal pada zamannya dan masih dipegang sampai sekarang, bahwa perdagangan, termasuk manufaktur, resisten terhadap analisis dan hanya dapat dilakukan dengan metode produksi kerajinan.
Dalam studi empirisnya, Taylor meneliti berbagai jenis pekerjaan manual. Sebagai contoh, sebagian besar penanganan material dalam jumlah besar dilakukan secara manual pada saat itu; peralatan penanganan material yang kita kenal sekarang sebagian besar belum dikembangkan.
Dia mengamati menyekop dalam pembongkaran gerbong kereta api yang penuh dengan bijih besi; mengangkat dan membawa dalam pemindahan babi besi di pabrik baja; inspeksi manual bola bantalan; dan lain-lain.
Dia menemukan banyak konsep yang tidak diterima secara luas pada saat itu. Sebagai contoh, dengan mengamati para pekerja, ia memutuskan bahwa kerja harus menyertakan waktu istirahat agar pekerja memiliki waktu untuk memulihkan diri dari kelelahan, baik fisik (seperti dalam menyekop atau mengangkat) maupun mental (seperti dalam kasus pemeriksaan bola). Pekerja diizinkan untuk beristirahat lebih banyak selama bekerja, dan produktivitas pun meningkat sebagai hasilnya.
Bentuk-bentuk manajemen ilmiah selanjutnya diartikulasikan oleh murid-murid Taylor, seperti Henry Gantt; insinyur dan manajer lainnya, seperti Benjamin S. Graham; dan ahli teori lainnya, seperti Max Weber. Karya Taylor juga kontras dengan upaya-upaya lain, termasuk karya Henri Fayol dan karya Frank Gilbreth, Sr. dan Lillian Moller Gilbreth (yang pada awalnya memiliki banyak kesamaan dengan Taylor, namun kemudian berbeda sebagai tanggapan atas penanganan hubungan antarmanusia yang tidak memadai oleh Taylorisme).
Ketentaraan
Manajemen ilmiah membutuhkan tingkat kontrol manajerial yang tinggi terhadap praktik kerja karyawan dan memerlukan rasio pekerja manajerial yang lebih tinggi terhadap buruh daripada metode manajemen sebelumnya. Manajemen yang berorientasi pada detail seperti itu dapat menyebabkan gesekan antara pekerja dan manajer.
Taylor mengamati bahwa beberapa pekerja lebih berbakat daripada yang lain, dan bahkan pekerja yang cerdas pun sering tidak termotivasi. Dia mengamati bahwa sebagian besar pekerja yang dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang berulang-ulang cenderung bekerja dengan kecepatan paling lambat yang tidak dihukum.
Laju kerja yang lambat ini telah diamati di banyak industri dan banyak negara dan telah disebut dengan berbagai istilah. Taylor menggunakan istilah “soldiering”, ilah yang mencerminkan cara wajib militer dalam mengikuti perintah, dan mengamati bahwa, jika dibayar dalam jumlah yang sama, pekerja akan cenderung melakukan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang paling lambat di antara mereka. Taylor mendeskripsikan soldiering sebagai “kejahatan terbesar yang dialami oleh kaum buruh...saat ini.
Hal ini mencerminkan gagasan bahwa para pekerja memiliki kepentingan pribadi atas kesejahteraan mereka sendiri, dan tidak mendapatkan keuntungan dari bekerja di atas tingkat kerja yang ditentukan jika hal itu tidak akan meningkatkan upah mereka. Oleh karena itu, dia mengusulkan bahwa praktik kerja yang telah dikembangkan di sebagian besar lingkungan kerja dibuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sangat tidak efisien dalam pelaksanaannya. Dia berpendapat bahwa studi waktu dan gerakan yang dikombinasikan dengan analisis dan sintesis rasional dapat menemukan satu metode terbaik untuk melakukan tugas tertentu, dan bahwa metode yang berlaku jarang sekali sama dengan metode terbaik ini. Yang terpenting, Taylor sendiri secara gamblang mengakui bahwa jika kompensasi setiap karyawan dikaitkan dengan hasil kerja mereka, maka produktivitas mereka akan meningkat.
Oleh karena itu, rencana kompensasinya biasanya mencakup upah borongan. Sebaliknya, beberapa pengadopsi studi waktu dan gerak yang muncul belakangan mengabaikan aspek ini dan mencoba untuk mendapatkan peningkatan produktivitas yang besar sementara memberikan sedikit atau bahkan tidak ada peningkatan kompensasi kepada tenaga kerja, yang berkontribusi pada kebencian terhadap sistem tersebut.
Produktivitas, otomatisasi, dan pengangguran
Seorang masinis di Tabor Company, sebuah perusahaan tempat Frederick Taylor menerapkan konsultasinya, sekitar tahun 1905
Taylorisme menyebabkan peningkatan produktivitas, yang berarti lebih sedikit pekerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah barang yang sama. Dalam jangka pendek, peningkatan produktivitas seperti yang dicapai oleh teknik efisiensi Taylor dapat menyebabkan gangguan yang cukup besar.
Hubungan tenaga kerja sering kali menjadi perdebatan mengenai apakah keuntungan finansial akan diperoleh pemilik dalam bentuk peningkatan laba, atau pekerja dalam bentuk peningkatan upah. Sebagai hasil dari penguraian dan dokumentasi proses manufaktur, perusahaan yang menggunakan metode Taylor mungkin dapat mempekerjakan pekerja berketerampilan lebih rendah, memperbesar jumlah pekerja dan dengan demikian menurunkan upah dan keamanan kerja.
Dalam jangka panjang, sebagian besar ekonom menganggap peningkatan produktivitas sebagai manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan, dan diperlukan untuk meningkatkan standar hidup konsumen secara umum. Pada saat Taylor melakukan penelitiannya, peningkatan produktivitas pertanian telah membebaskan sebagian besar tenaga kerja untuk sektor manufaktur, yang memungkinkan para pekerja tersebut untuk membeli jenis barang konsumsi baru daripada bekerja sebagai petani subsisten. Pada tahun-tahun berikutnya, peningkatan efisiensi manufaktur akan membebaskan sebagian besar tenaga kerja untuk sektor jasa.
Jika ditangkap sebagai keuntungan atau upah, uang yang dihasilkan oleh perusahaan yang lebih produktif akan digunakan untuk membeli barang dan jasa baru; jika persaingan pasar bebas memaksa harga turun mendekati biaya produksi, konsumen secara efektif akan mendapatkan keuntungan dan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa baru.
Bagaimanapun juga, perusahaan dan industri baru bermunculan untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan, dan karena tenaga kerja yang dibebaskan dapat mempekerjakan pekerja. Namun, manfaat jangka panjang tersebut tidak menjamin bahwa setiap pekerja yang dirumahkan akan mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang sama atau lebih baik dari pekerjaan mereka yang lama, karena hal ini mungkin memerlukan akses ke pendidikan atau pelatihan kerja, atau pindah ke daerah lain di mana industri baru sedang berkembang.
Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan baru karena ketidakcocokan seperti ini dikenal sebagai pengangguran struktural, dan para ekonom memperdebatkan sejauh mana hal ini terjadi dalam jangka panjang, jika ada, serta dampaknya terhadap ketidaksetaraan pendapatan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan.
Meskipun tidak diramalkan oleh para pendukung awal manajemen ilmiah, penguraian terperinci dan dokumentasi metode produksi yang optimal juga membuat otomatisasi proses menjadi lebih mudah, terutama proses fisik yang nantinya akan menggunakan sistem kontrol industri dan kontrol numerik.
Globalisasi ekonomi yang meluas juga menciptakan peluang bagi pekerjaan untuk dialihdayakan ke daerah dengan upah yang lebih rendah, dengan transfer pengetahuan menjadi lebih mudah jika metode yang optimal sudah didokumentasikan dengan jelas. Terutama ketika upah atau perbedaan upah tinggi, otomatisasi dan offshoring dapat menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan dan pertanyaan serupa tentang siapa yang diuntungkan dan apakah pengangguran teknologi tetap ada atau tidak.
Karena otomatisasi sering kali paling cocok untuk tugas-tugas yang berulang dan membosankan, dan juga dapat digunakan untuk tugas-tugas yang kotor, berbahaya, dan merendahkan, para pendukungnya percaya bahwa dalam jangka panjang hal ini akan membebaskan pekerja manusia untuk melakukan pekerjaan yang lebih kreatif, lebih aman, dan lebih menyenangkan.
Taylorisme dan serikat pekerja
Sejarah awal hubungan tenaga kerja dengan manajemen ilmiah di AS dijelaskan oleh Horace Bookwalter Drury:
... Untuk waktu yang lama, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada [konflik] langsung antara manajemen ilmiah dan buruh yang terorganisir... [Namun] Salah satu ahli yang paling terkenal pernah berbicara kepada kami dengan puas tentang bagaimana, di sebuah pabrik tertentu di mana terdapat sejumlah anggota serikat pekerja, organisasi buruh, setelah diperkenalkannya manajemen ilmiah, secara bertahap hancur.
... Dari tahun 1882 (ketika sistem ini dimulai) hingga 1911, periode sekitar tiga puluh tahun, tidak ada satu pun pemogokan di bawah sistem ini, dan ini terlepas dari kenyataan bahwa sistem ini dijalankan terutama di industri baja, yang mengalami banyak sekali gangguan. Sebagai contoh, dalam pemogokan umum di Philadelphia, hanya satu orang yang keluar di pabrik Tabor [yang dikelola oleh Taylor], sementara di toko-toko Lokomotif Baldwin di seberang jalan ada dua ribu orang yang mogok kerja.
... Penentangan yang serius dapat dikatakan dimulai pada tahun 1911, segera setelah kesaksian tertentu yang disampaikan di hadapan Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian [oleh Harrington Emerson] mengungkapkan kepada negara tersebut tentang gerakan yang kuat yang mengarah pada manajemen ilmiah. Para pemimpin buruh nasional, yang sadar akan apa yang akan terjadi di masa depan, memutuskan bahwa gerakan baru ini merupakan ancaman bagi organisasi mereka, dan sekaligus meresmikan sebuah serangan ... yang berpusat pada pemasangan manajemen ilmiah di gudang senjata pemerintah di Watertown.
Pada tahun 1911, buruh yang terorganisir meletus dengan penentangan yang kuat terhadap manajemen ilmiah,[4] termasuk dari Samuel Gompers, pendiri dan presiden Federasi Buruh Amerika (AFL).
Setelah para ahli waktu dan gerak menyelesaikan studi mereka tentang tugas tertentu, para pekerja hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berpikir lebih lanjut, bereksperimen, atau memberikan saran. Taylorisme dikritik karena mengubah pekerja menjadi “robot” atau “mesin”, membuat pekerjaan menjadi monoton dan tidak memuaskan dengan melakukan satu pekerjaan kecil dan didefinisikan secara kaku alih-alih menggunakan keterampilan yang kompleks dengan seluruh proses produksi yang dilakukan oleh satu orang. “Semakin ‘maju’ perkembangan industri... meningkatkan anomali atau pembagian kerja yang dipaksakan,” kebalikan dari apa yang dipikirkan Taylor sebagai dampaknya. Beberapa pekerja juga mengeluh tentang dipaksa bekerja dengan kecepatan yang lebih tinggi dan memproduksi barang dengan kualitas yang lebih rendah.
Karena penerapannya sebagian di gudang senjata pemerintah, dan pemogokan oleh serikat pekerja terhadap beberapa fiturnya saat diperkenalkan di pengecoran di Watertown Arsenal, “manajemen ilmiah” menerima banyak publisitas.
Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk sebuah komite, yang terdiri dari anggota Kongres William B. Wilson, William C. Redfield, dan John Q. Tilson untuk menyelidiki sistem yang diterapkan di Watertown Arsenal. Dalam laporannya kepada Kongres, komite ini mendukung pendapat Partai Buruh bahwa sistem ini memaksa pekerja untuk bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahwa fitur-fitur disiplinernya bersifat sewenang-wenang dan kasar, dan bahwa penggunaan stop-watch dan pembayaran bonus merugikan kedewasaan dan kesejahteraan pekerja. Pada sidang Kongres berikutnya, sebuah tindakan disahkan yang melarang penggunaan stop-watch lebih lanjut dan pembayaran premi atau bonus kepada pekerja di perusahaan pemerintah.
Ketika Komisi Hubungan Industrial federal mulai bekerja, diputuskan bahwa penyelidikan lebih lanjut mengenai “manajemen ilmiah” harus dilakukan, dan Robert F. Hoxie, Profesor Ekonomi di Universitas Chicago, dipilih untuk melakukan pekerjaan tersebut. [ ... ]
Hoxie akan mencurahkan waktu satu tahun untuk melakukan penyelidikan, dan [...] dianggap lebih baik jika ia didampingi oleh dua orang [...]
Salah satu dari mereka yang ditunjuk adalah Tuan Robert G. Valentine [sebelumnya Komisaris Urusan India, tetapi “pada saat ini menjadi konsultan manajemen dalam praktik pribadi” menurut Aitken] [ ...]
Pakar lainnya adalah seorang anggota serikat buruh, dan saya [John P. Frey] merasa terhormat dengan penunjukan tersebut.
- John P. Frey. “Manajemen Ilmiah dan Perburuhan”. American Federationist. 22 (4): 257 (April 1916)
Watertown Arsenal di Massachusetts memberikan contoh penerapan dan pencabutan sistem Taylor di tempat kerja, karena adanya penolakan dari para pekerja. Pada awal abad ke-20, pengabaian di toko-toko di Watertown meliputi kepadatan yang berlebihan, pencahayaan yang redup, kurangnya peralatan dan perlengkapan, serta strategi manajemen yang dipertanyakan di mata para pekerja. Frederick W. Taylor dan Carl G. Barth mengunjungi Watertown pada bulan April 1909 dan melaporkan hasil pengamatan mereka di toko-toko tersebut.
Kesimpulan mereka adalah untuk menerapkan sistem manajemen Taylor pada toko-toko tersebut untuk memberikan hasil yang lebih baik. Upaya untuk menerapkan sistem Taylor dimulai pada bulan Juni 1909. Selama bertahun-tahun mempelajari dan mencoba meningkatkan efisiensi pekerja, kritik mulai berkembang.
Para pekerja mengeluh karena harus bersaing satu sama lain, merasa tegang dan kesal, dan merasa sangat lelah setelah bekerja. Pada bulan Juni 1913, para pekerja di Watertown Arsenal mengajukan petisi untuk menghapuskan praktik manajemen ilmiah di sana. Sejumlah penulis majalah yang menyelidiki dampak dari manajemen ilmiah menemukan bahwa “kondisi di toko-toko yang diselidiki sangat kontras dengan kondisi di pabrik-pabrik lain.
Sebuah komite Dewan Perwakilan Rakyat AS menyelidiki dan melaporkan pada tahun 1912, menyimpulkan bahwa manajemen ilmiah memang memberikan beberapa teknik yang berguna dan menawarkan saran organisasi yang berharga, [perlu kutipan untuk memverifikasi] tetapi juga memberikan manajer produksi tingkat kekuasaan yang tidak terkendali yang sangat berbahaya.
Setelah survei sikap terhadap para pekerja mengungkapkan tingkat kebencian dan permusuhan yang tinggi terhadap manajemen ilmiah, Senat melarang metode Taylor di gudang senjata.
Taylor memiliki pandangan yang sebagian besar negatif terhadap serikat pekerja, dan percaya bahwa serikat pekerja hanya menyebabkan penurunan produktivitas. Upaya untuk menyelesaikan konflik dengan para pekerja termasuk metode kolektivisme ilmiah, membuat perjanjian dengan serikat pekerja, dan gerakan manajemen personalia.
Hubungan dengan Fordisme
Sering diasumsikan bahwa Fordisme berasal dari karya Taylor. Taylor tampaknya membuat asumsi ini sendiri ketika mengunjungi pabrik Ford Motor Company di Michigan tidak terlalu lama sebelum dia meninggal, tetapi kemungkinan besar metode di Ford berkembang secara independen, dan bahwa setiap pengaruh dari karya Taylor adalah pengaruh tidak langsung yang paling baik.[30] Charles E. Sorensen, seorang kepala sekolah perusahaan selama empat dekade pertama, menyangkal adanya hubungan apa pun.
Ada keyakinan di Ford, yang tetap dominan hingga Henry Ford II mengambil alih perusahaan pada tahun 1945, bahwa para ahli dunia tidak berharga, karena jika Ford mendengarkan mereka, Ford akan gagal mencapai kesuksesan besarnya.
Henry Ford merasa bahwa ia telah berhasil terlepas dari, bukan karena, para ahli, yang telah mencoba menghentikannya dengan berbagai cara (tidak setuju dengan poin harga, metode produksi, fitur mobil, pembiayaan bisnis, dan masalah lainnya).
Sorensen kemudian meremehkan Taylor dan memasukkannya ke dalam kategori ahli yang tidak berguna. Sorensen sangat menghargai penjual peralatan mesin New England, Walter Flanders, dan memujinya atas tata letak denah yang efisien di Ford, dan menyatakan bahwa Flanders tidak tahu apa-apa tentang Taylor.
Flanders mungkin telah terpapar semangat Taylorisme di tempat lain, dan mungkin terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak mengutipnya ketika mengembangkan teknik produksinya. Terlepas dari itu, tim Ford tampaknya secara mandiri menciptakan teknik produksi massal modern pada periode 1905-1915, dan mereka sendiri tidak mengetahui adanya pinjaman dari Taylorisme. Mungkin hanya dengan melihat ke belakang kita dapat melihat semangat yang (secara tidak langsung) menghubungkan Fordisme yang sedang berkembang dengan gerakan efisiensi lainnya selama dekade 1905-1915.
Adopsi dalam ekonomi terencana
Manajemen ilmiah menarik bagi para manajer ekonomi terencana karena perencanaan ekonomi pusat bergantung pada gagasan bahwa biaya yang masuk ke dalam produksi ekonomi dapat diprediksi secara tepat dan dapat dioptimalkan dengan desain.
Disadur dari: en.wikipedia.org
Ilmu dan Teknologi Hayati
Keajaiban Keanekaragaman Hayati dan Ancaman Kepunahan
Dipublikasikan oleh Anisa pada 28 Februari 2025
"Keanekaragaman hayati"—“keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah"—adalah istilah yang paling sering digunakan untuk menggantikan definisi yang lebih jelas sebelumnya, yaitu keanekaragaman spesies dan kekayaan spesies . Keuntungan dari definisi ini adalah bahwa itu menggambarkan sebagian besar situasi dan memberikan gambaran yang luas tentang jenis keanekaragaman hayati yang telah dikenal selama bertahun-tahun.
Keanekaragaman hayati, juga disebut biodiversitas, adalah variasi dan variabilitas kehidupan di Bumi. Variasi biasanya diukur pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Ekosistem hutan tropis menampung sekitar 90% spesies yang ada di Bumi, meskipun ekosistem ini hanya mencakup 10% dari permukaan Bumi, biodiversitas daratan (terestrial) biasanya lebih besar di sekitar khatulistiwa karena iklim yang hangat dan produktivitas primer (aliran energi) yang tinggi. Di sepanjang pantai barat Samudra Pasifik, di mana suhu permukaan laut paling tinggi, dan di pita lintang tengah setiap lautan, keanekaragaman hayati laut biasanya tertinggi. Gradien lintang juga memengaruhi keanekaragaman spesies. Keanekaragaman hayati umumnya mengelompok di titik panas, dan telah berkembang seiring waktu, tetapi kemungkinan akan melambat di masa depan.
Kepunahan massal biasanya disebabkan oleh perubahan lingkungan yang cepat. Lebih dari 99,9 persen dari semua spesies yang pernah ada di Bumi, yang berjumlah lebih dari lima miliar spesies, diperkirakan telah punah. Jumlah spesies saat ini diperkirakan berkisar antara 10 juta hingga 14 juta, dan sekitar 1,2 juta spesies telah diidentifikasi, tetapi lebih dari 86% di antaranya belum dideskripsikan dengan baik. Pada Mei 2016, para ilmuwan menyatakan bahwa hanya seperseribu dari satu triliun spesies yang telah dideskripsikan dari total yang diperkirakan ada di Bumi saat ini. Menurut perkiraan, ada 5,0 x 1037 pasangan basa DNA dengan berat 50 miliar ton di Bumi. Di sisi lain, diperkirakan bahwa massa total biosfer adalah 4 TtC, atau triliun ton karbon. Pada Juli 2016, para ilmuwan menemukan set 355 gen dari leluhur universal terakhir (LUCA) dari semua organisme yang hidup di Bumi.
Perkiraan usia Bumi adalah 4,54 miliar tahun.Fakta yang tidak dapat disangkal menunjukkan bahwa kehidupan di Bumi pertama kali muncul paling tidak 3,5 miliar tahun yang lalu, selama era Eoarkean, saat kerak geologis mulai mengeras setelah meleleh pada era Hadean. Fosil tikar mikrob ditemukan di batupasir di Australia Barat berumur 3,48 miliar tahun. Grafit ditemukan di batuan metasedimentari di Greenland Barat berumur 3,7 miliar tahun, dan pada tahun 2015, ditemukan "sisa-sisa kehidupan biotik" di batuan berumur 4,1 miliar tahun di Australia bagian barat."Jika kehidupan muncul relatif cepat di Bumi... maka ia bisa menjadi hal yang umum di alam semesta," kata seorang ilmuwan.
Keanekaragaman hayati telah menurun secara drastis selama lima kepunahan massal besar dan beberapa peristiwa kecil sejak kehidupan dimulai di Bumi. Selama Eon Fanerozoikum, yang berlangsung selama 540 juta tahun terakhir, pertumbuhan keanekaragaman hayati meningkat dengan cepat. Ini terjadi selama letusan Kambrium, saat kebanyakan filum organisme multiseluler pertama kali muncul. Kepunahan massal, yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadi beberapa kali selama 400 juta tahun berikutnya. Pada periode Karbon, hutan hujan hancur, menyebabkan kehilangan kehidupan. Kepunahan terburuk, kepunahan Perm–Trias, terjadi 251 juta tahun lalu; organisme vertebrata membutuhkan 30 juta tahun untuk pulih darinya. Kepunahan terakhir, kepunahan Kapur–Paleogen, terjadi 65 juta tahun lalu, lebih menarik dibandingkan kepunahan lainnya karena mengakibatkan kepunahan dinosaurus non-avian.
Pengurangan keanekaragaman hayati dan hilangnya keanekaragaman genetik telah terjadi sejak munculnya manusia. Proses ini dikenal sebagai kepunahan Holosen, yang berarti pengurangan yang terutama disebabkan oleh manusia, terutama penghancuran habitat.Sebaliknya, keanekaragaman hayati baik untuk kesehatan manusia dalam berbagai cara, meskipun efek negatifnya juga dipelajari.Seratus
PBB menetapkan 2011–2020 sebagai Dekade Keanekaragaman Hayati PBB dan 2021–2030 sebagai Dekade Restorasi Ekosistem PBB. Menurut Laporan Penilaian Global tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem oleh IPBES pada tahun 2019, 25% spesies terancam punah karena aktivitas manusia.
Keanekaragaman hayati tidak tersebar secara merata di seluruh dunia. Sifatnya sangat beragam di mana pun kita berada di Bumi. Keanekaragaman setiap makhluk hidup (biota) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini termasuk suhu, curah hujan, ketinggian, tanah, geografi, dan keberadaan spesies lain. Ilmu biogeografi berfokus pada bagaimana organisme, spesies, dan ekosistem tersebar di seluruh dunia.
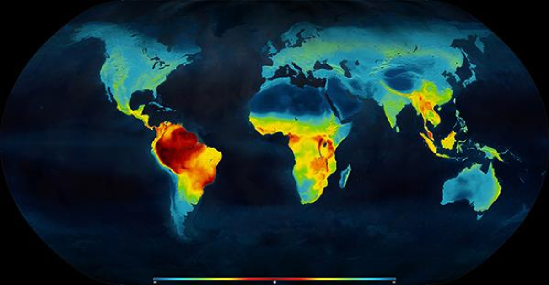
Hutan hujan yang sejak lama memiliki iklim basah, seperti Taman Nasional Yasuní di Ekuador, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tingkat keanekaragaman hayati secara konsisten lebih tinggi di daerah tropis dan di beberapa wilayah lokal lainnya, seperti Wilayah Tanjung Floristik, dan umumnya lebih rendah di daerah kutub.
Keanekaragaman hayati di darat diperkirakan 25 kali lebih besar dibandingkan dengan keanekaragaman hayati di lautan. Jumlah total spesies di Bumi diperkirakan sebesar 8,7 juta, dengan 2,1 juta spesies diperkirakan hidup di lautan, tetapi perkiraan ini tampaknya kurang mewakili keanekaragaman mikroorganisme.
Titik panas keanekaragaman hayati adalah daerah yang memiliki banyak spesies endemik yang telah mengalami pengrusakan habitat yang signifikan. Norman Myers pertama kali menggunakan istilah "titik panas" (hotspot) pada tahun 1988.Meskipun titik panas ada di seluruh dunia, mayoritas di antaranya berada di hutan dan sebagian besar berada di wilayah tropis.
Hutan Atlantik Brasil adalah salah satu titik panas dengan sekitar 20.000 spesies tumbuhan, 1.350 vertebrata, dan jutaan serangga, sekitar setengahnya tidak ditemukan di tempat lain. Pulau India dan Madagaskar juga sangat terkenal. Keanekaragaman hayati Kolombia sangat kaya, dengan tingkat spesies tertinggi di dunia berdasarkan satuan luas dan jumlah endemik terbesar—spesies yang secara alami tidak ditemukan di negara lain—di dunia. Kolombia memiliki lebih dari 1.900 spesies burung, sekitar 10% dari spesies organisme di Bumi, lebih banyak daripada di Eropa dan Amerika Utara. Ini juga memiliki 14% spesies amfibi, 10% spesies mamalia, dan 18% spesies burung di dunia. Orang-orang asli Madagaskar tinggal di hutan kering dan hutan hujan dataran rendah. Banyak spesies dan ekosistem pulau ini berevolusi secara mandiri karena mereka terpisah dari daratan Afrika 66 juta tahun yang lalu.Indonesia, yang memiliki 17.000 pulau, memiliki luas 1.354.555 mil persegi, atau 1.904.560 km2, dan memiliki 10% dari tumbuhan berbunga, 12% dari mamalia, dan 17% dari reptil, amfibi, dan burung di dunia.Banyak wilayah dengan keanekaragaman hayati dan endemisme yang luas berasal dari habitat yang tidak biasa yang membutuhkan adaptasi, seperti rawa gambut di Eropa Utara atau pegunungan Alpen di pegunungan tinggi. Mengukur perbedaan keanekaragaman hayati sangat sulit. Ada kemungkinan bahwa bias seleksi di antara para peneliti akan menyebabkan penelitian empiris yang tidak akurat untuk perkiraan kontemporer tentang keanekaragaman hayati.
Sumber: